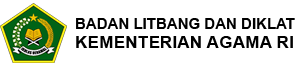Di Balik Kisah Pembuatan Film Tondok Solata Kerukunan Umat Beragama di Toraja (Bersambung)

Oleh: Muh. Irfan Syuhudi (Peneliti Balai Litbang Agama Makassar)
Peneliti Berakting
HUJAN rintik-rintik seolah menyambut kedatangan kami di Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin, 25 Februari 2019. Kami tiba di hotel tempat menginap, sekitar pukul 22.00 Wita, dalam perjalanan dari Kota Makassar. Perjalanan Makassar - Toraja yang berjarak 314,9 kilometer, dan ditempuh naik mobil, memakan waktu sekitar delapan jam. Begitu tiba di hotel, tubuh kami semua terasa lelah.
Selama sepekan, 25 Februari - 3 Maret 2019, kami ke Toraja untuk membuat film bertema kerukunan antarumat beragama. Ini merupakan program pengembangan (workshop) peneliti Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Bidang kami memangconcern terhadap fenomena kerukunan antarumat beragama, terutama di Kawasan Timur Indonesia, sesuai wilayah kerja kantor kami.
Kami memilih dua lokasi di Kabupaten Toraja, yakni Tana Toraja dan Toraja Utara. Jarak antara dua daerah ini sebenarnya tidak terlalu jauh. Tidak sampai satu jam dengan kendaraan darat. Hanya, jalannya lebih banyak menanjak, karena terletak di daerah ketinggian.
Lalu, alasan pembuatan film di daerah ini, karena Toraja sejak dulu dikenal dengan kehidupan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Hingga kini, masyarakat hidup akur dan damai tanpa adanya sekat-sekat identitas sosial (etnis dan agama).
Bisa dikatakan, Toraja melambangkan miniatur Indonesia. Selain beragam etnis berbaur dan saling berinteraksi, agama versi negara, plus agama lokal (Aluk Todolo), juga hidup berdampingan. Malah, masih sering ditemui orang berbeda keyakinan hidup rukun dan damai dalam satu atap.
Setelah beberapa kali rapat tim yang terdiri atas 10 orang; Muh. Irfan Syuhudi, Baso Marannu, Syamsurijal, Sitti Arafah, Sabara, Paisal, Muh. Ali Saputra, Muh. Dachlan, Djazuli, dan Darwis, disepakatilah film ini diberi judul: “Tondok Solata Kerukunan Umat Beragama di Toraja”. Secara harfiah, “Tondok Solata” dalam bahasa Toraja diartikan “Kampung Teman” atau “Kampung Persahabatan”.
Film ini akan melibatkan semua peneliti di Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, ditambah beberapa mahasiswa dan dosen di Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Toraja. Jadi, bagi peneliti Litbang Agama Makassar dan mahasiswa/i dan dosen STAKN, ini adalah pengalaman pertama mereka semua berakting di depan kamera.
Keesokan hari, sekitar pukul 09.00 Wita, di saat badan masih terasa capek akibat perjalanan kemarin, Sutradara film, Baso Marannu, meminta kami untuk rapat terkait adegan film apa yang dilakukan hari ini. Kami juga janjian dengan dosen STAKN, Rannu, ...., Naomi.., dan mahasiswa. Bahkan, hari ini juga, sutradara bakal menyeleksi tokoh perempuan lokal yang diplot memerankan tokoh utama.
Sambil menunggu kedatangan dosen dan mahasiswa STAKN di hotel, kami menggelar rapat tim di salah satu lobbi hotel, setelah terlebih dulu berdoa agar pembuatan film dapat berjalan lancar dan tanpa kendala.
“Om Syamsurijal, Jam 10 nanti kita akan melakukan adegan pertama. Siap-siap saja, ya!” kata Baso Marannu. Peneliti Litbang Agama, Syamsurijal, dalam film ini ditunjuk sebagai tokoh utama, memerankan seorang peneliti Antropologi. Bersama dua rekannya, Sabara dan Irfan (peneliti Litbang Agama), mereka berkunjung ke daerah, yang terkenal dengan “kotor” (kopi Toraja) ini.
Selama ini, Ijal dan kawan-kawan cuma mengetahui kerukunan umat beragama di Toraja melalui bacaan buku teks, hasil penelitian, dan cerita-cerita temannya, yang pernah menginjakkan kaki di Toraja. Dari semua informasi tersebut, mereka kemudian menjadi penasaran, dan akhirnya memutuskan ingin melihat langsung praktik kerukunan antarumat beragama di daerah ini.
Adegan pertama dilakukan di dalam kamar. Bersama seorang temannya asal Toraja, Dahlan, Ijal terlihat menyaksikan berita di televisi mengenai konflik antarumat beragama di Tolikara, Papua.
***
Syuting film, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Selama ini, semua pemain adalah penggemar, sekaligus "kritikus" film. Kalau ada film bagus akan dipuja-puja. Giliran habis menonton film yang dianggap buruk, mereka bakal mengeritiknya habis-habisan.
Nah, kali ini, mereka kena batunya. Rupanya, untuk memerankan satu adegan itu, ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sangat susah. Apalagi, bagi orang-orang yang tidak pernah main film. Jangankan main film, melihat dari dekat cara pembuatan film saja, rasa-rasanya mereka juga belum pernah. Hehehe.
Bayangkan, satu adegan saja yang terlihat sangat sederhana, seperti menonton televisi di dalam kamar, atau mengambil sebuah laptop di atas meja, terpaksa harus diulang berkali-kali. Sampai-sampai, pameran utamanya kerap mengernyitkan kening. Dahlan, yang juga kebagian peran di situ, ikut-ikutan juga mengeluh, meski setelah itu keduanya tertawa. "Padahal, saya rasa bagus mi tadi itu aktingku. Tapi kok Om sutradara masih bilang belum bagus," kata Ijal.
Belum lagi adegan lain yang tampak mudah, tetapi harus diulang hingga empat kali. Contohnya, adegan keluar dan masuk ke dalam mobil. "Masa' mau masuk ke dalam mobil saja mesti diulang berkali-kali. Kayaknya, lebih asik jadi peneliti.Hehehe.." kata Sabara.
Selama syuting, para pemain dan kru saling mengganggu. Kadangkala, dan bahkan sering, beberapa adegan terpaksa diulang, lantaran pemain yang kena giliran memerankan adegan, tidak tahan menahan godaan teman-temannya.
Alhasil, sang sutradara, Baso Marannu, kadang dibuat geleng-geleng kepala melihat aksi pemainnya. Suara Om Basmar, panggilan akrab Baso Marannu, pun terdengar serak akibat sering teriak kencang "action" sambil memegang papan clapper board.
"Ciee.. Ciee.. Yang mau jadi artis nasional menggantikan Nicolas Saputra. Hihihi.." celutuk seorang pemain menggoda. Spontan, sang pemain tak bisa menahan senyum. Padahal, peran yang ia lakoni mengharuskan memasang mimik serius.
Tidak ada casting-castingan. Semua serba dadakan di lapangan. Sutradara mengarahkan, pemain tinggal melaksanakan apa yang diinstruksikan. Wajah Desi sempat memucat waktu dipilih oleh sutradara untuk memerankan tokoh utama perempuan lokal. Ia mengaku tak punya bakat berakting. Namun, berkat tangan dingin sutradara dan asistennya, Djazuli dan Darwis, Desi yang tercatat sebagai mahasiswi semester delapan STAKN itu, akhirnya tampil percaya diri.
Seru juga menentukan rangkaian alur cerita sebuah kisah film. Adegan demi adegan mesti berurut satu demi satu. Itu agar jalan ceritanya terlihat nyambung, dan menjadi satu kesatuan.
Ibarat orang ingin pergi ke pasar, dan di situ cuma ada satu-satunya jalan, sedangkan jalanan yang akan dilewati macet.
Maka, jalan ini harus dilalui pelan-pelan, dan penuh kesabaran. Tidak boleh melompat, dan, huffss.. langsung tiba di pasar. Menentukan alur cerita perlu didiskusikan matang-matang. Tak heran, perbincangan ini selalu saja berlangsung "hangat". Bahkan, ia tidak mengenal tempat dan waktu. Kadang sehabis sarapan, sedang ngopi-ngopi di lobbi hotel, serta di lokasi syuting.
Yang dibicarakan bukan cuma menentukan tema besarnya. Tetapi juga, menyangkut plot cerita setiap detail adegan. Misalkan, bagaimana gaya pemain pada saat mengobrol dengan Imam Masjid Agung Rantepao, Haji Mujahidin? Apakah pas bertemu langsung berjabat tangan, dan kemudian mengobrol seperti biasa, sambil duduk bersila atau berdiri?
Ataukah, ada hal-hal lain yang harus dilakukan terlebih dahulu? Ya, misalkan, ikut shalat berjamaah di masjid, dan seusai shalat mendatangi imam masjid. Lalu, sebelum mengajak imam berbicara, apakah perlu juga diperlihatkan proses memperkenalkan diri pemain? Duh. Ribet, kan? Hehe.
Kemudian, muncul lagi pertanyaan, saat adegan mengobrol dengan Pendeta Daud Sangka Palisungang, kira-kira di mana akan bertemu? Apakah di rumahnya, di gereja, ataukah di tongkonan? Terus, kalau sudah bertemu dan mengobrol, bagaimana sebaiknya posisi narasumber dan pemain? Apakah saling berhadap-hadapan, mengobrol sambil berjalan, atau apa? Selanjutnya, apa topik-topik yang ditanyakan nanti?
Sebab, boleh jadi, apa yang telah dirancang sebelumnya, ternyata mendadak berubah setelah tiba di lokasi. Termasuk juga, baju apa yang akan dipakai saat syuting. Jangan sampai, baju yang dikenakan sama, sementara settingan syutingnya pada adegan yang lain.
Setelah shalat subuh, kru dan beberapa pemain langsung pergi untuk pengambilan spot matahari terbit. Tak tanggung-tanggung, pengambilan gambar munculnya matahari harus direkam langsung. Disepakatilah pengambilan gambar dilakukan di objek wisata Buntu Singki, Toraja Utara. Namun, dibutuhkan kekuatan ekstra prima untuk mencapai puncaknya. Sebab, ada 500 anak tangga yang harus dilewati, sehingga bila dihitung bolak-balik, ada sekitar seribu anak tangga. Wow!
Peneliti Litbang Agama dan juga pemeran film, Sitti Arafah dan Paisal, yang ikut naik ke puncak Buntu Singki, mengaku kedua betis dan telapak kakinya terasa bengkak. Mereka beberapa kali berhenti di tengah jalan dengan napas ngos-ngosan. Namun, begitu menginjakkan kaki di atas, dan menyaksikan keindahan view-nya, sakit di kakinya spontan hilang. Apalagi, mereka bisa sepuas-sepuasnya berpose di situ, sembari melihat langsung detik-detik matahari terbit dari daerah ketinggian. (*/Bersambung)
M. Irfan/diad