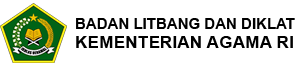Ironi Keberagamaan Umat

Oleh:
Edi Junaedi, Peneliti Agama dan Masyarakat
Deputi Kebijakan Pembangunan BRIN
Indeks Kesalehan Sosial Umat Beragama (IKSUB) Tahun 2022 telah dirilis oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama hari Selasa (16/8/2022) lalu dalam sebuah seminar yang diadakan di Jakarta. Temuan Evaluasi IKSUB ini secara nasional bisa dibilang sangat menggembirakan dengan skor 84,55. Angka itu termasuk dalam kategori “sangat baik”.
Skor rata-rata nasional tersebut didapat dari skor beberapa dimensi yang mendukungnya, antara lain: relasi dengan negara dan pemerintah (91,41), menjaga etika dan budi pekerti (89,97), relasi antar manusia/kebhinekaan (86,63), kepedulian dan solidaritas sosial (78,73), dan melestarikan lingkungan (75,98).
Sebagaimana dijelaskan dalam desain operasionalnya, secara metodologis evaluasi dalam bentuk survei ini menyasar kepada umat beragama yang enam, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Lokus penelitian dipilih beberapa kota secara random yang dominan masing-masing umat beragamanya. Untuk umat Islam misalnya, lokus yang terpilih di antaranya adalah Kota Makassar dan Kota Bandung, sedangkan Kota Denpasar terpilih sebagai salah satu lokus umat Hindu. Rumah ibadah masing-masing agama dijadikan sebagai primary sampling unit (PSU)-nya. Dari masing-masing rumah ibadah yang terpilih diwawancarai lima repsonden yang terdiri dari tiga orang jemaah, satu orang pengurus rumah ibadah, dan satu orang tokoh agama setempat.
Realitas Keagamaan yang Ironis
Data di atas sekilas lalu selaras dengan fenomena keberagamaan umat kita terakhir yang ghirah-nya semakin meningkat. Di kalangan umat Islam misalnya, acara dakwah di berbagai media begitu semarak, masjid-masjid sekarang banyak dipadati jemaah setiap salat lima waktu, dan berjilbab menjadi pilihan muslimah di seantero negeri ini, yang bukan lagi sebatas gaya hidup baru muslimah perkotaan tapi juga pedesaan.
Namun di sisi lain, realitas sosial umat kita justru menampakkan wajah yang kontras dengan skor indeks dan semangat keberagamaan di atas. Kasus pembunuhan yang menggambarkan begitu mudahnya menghilangkan nyawa orang lain, kasus kekerasan seksual oleh pimpinan pondok pesantren di Bandung dan Jombang, serta kasus operasi tangkap tangan (OTT) Rektor Universitas Lampung (Unila) oleh KPK yang diduga melakukan tindakan korupsi dengan memungut biaya kelulusan masuk kampus, adalah di antara anomali sosial umat kita terakhir.
Belum lagi, data ujaran kebencian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menunjukkan fakta yang memprihatinkan, konten mengenai ujaran Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sebanyak 3.640 konten sejak tahun 2018, demikian terungkap pada konferensi pers virtual dari Media Center Kantor Kementerian Kominfo di Jakarta (26/04/2021) lalu.
SETARA Institute mencatat, pada tahun 2021 secara keseluruhan kumpulan data menunjukkan ada penurunan jumlah pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Pada tahun 2021 tercatat ada 171 peristiwa pelanggaran dan 318 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Bagaimanapun adanya fakta tersebut menunjukkan fenomena konflik keagamaan yang masih terjadi di tengah umat beragama kita (Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2021, SETARA Institute).
Dalam Siaran Pers “Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan”, Komnas Perempuan mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badilag. Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus.
Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730. Data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).
Sebagai masyarakat beragama, di mana sebenarnya nilai-nilai agama yang mereka yakini dan fahami diletakkan? Sebuah ironi sosial keagamaan yang kita prihatinkan bersama dan harus dicari solusinya. Faktanya, agama belum memberikan pengaruh pada kehidupan sosial umat beragama bangsa ini. Umat beragama kita mengalami ironi dalam realitas sosialnya.
Keberagamaan yang Formalis-Simbolik
Kita meyakini, secara umum agama menjadi sumber pokok nilai kemaslahatan bagi kehidupan. Namun demikian, nilai-nilai tersebut tidak bisa dengan sendirinya mewujud dalam praktek hidup manusia. Nilai, gagasan, dan spirit yang diperkenalkan agama masih bersifat pasif, sedangkan operasionalisasi nilai-nilai agama tersebut menjadi tugas berat para pemeluknya. Di sinilah salah satu letak masalahnya.
Menurut Soedjatmoko (1994), harus dibedakan antara kekayaan khazanah, pikiran, dan kaidah-kaidah agama yang ada dalam kitab suci, atau buku agama, dengan kemampuan pemeluk atau lembaganya untuk memegang peran peradaban, atau pengendali sejarah. Dalam konteks Islam, Nurcholish Madjid (Cak Nur) membedakan keduanya dengan Islam sebagai doktrin dan Islam sebagai peradaban. Sayyed Hoessein Nasr dengan istilah “Islam Ideal” dan “Islam Realita”. Yang pertama dipandang ideal berupa wahyu yang tercantum dalam Al-Qur’an, sementara yang kedua merupakan Islam yang diamalkan yang bisa jadi tidak seperti gambaran idealnya.
Bagi Cak Nur, adanya diskrepansi antara ajaran Islam yang luhur—yang tidak mengenal diskriminasi, yang menghormati hak asasi, yang mendorong keadilan, musyawarah, toleransi, dan mengkampanyekan penghargaan pada keragaman—dengan kenyataan historiknya, disebabkan karena umat Islam “menyandra” ajaran luhur tersebut. Padahal sejatinya, seperti diakui Ghulam Farid Malik, Islam is religion of peace and justice, not permit extremism, violence or terrorism in all spheres of life (Dadang Kahmad, 2006).
Dalam pandangan Cak Nur (1993), di antara problem keagamaan ialah pandangan dunia (vision de monde) yang keliru. Padahal sejatinya, ia sangat penting untuk mengarahkan hidup. Khalil Khavari seperti ditulis Ary Ginanjar (2007), melihat bahwa terjadinya spiritual pathology atau spiritual illness pada manusia modern lebih disebabkan karena kesalahan orientasi dalam menjalani hidup. Dengan demikian, pencerahan berkelanjutan diperlukan dalam mendesain orientasi hidup yang berkualitas, suatu bentuk kehidupan yang penuh harmoni, dan memelihara spirit keragaman.
Di sisi lain, penulis tertarik pendapat Wahyuddin Halim, salah seorang dosen UIN Alauddin Makassar dalam sebuah wawancara penelitian tentang kesalehan sosial umat beragama. Ironi keberagamaan umat kita terakhir sesungguhnya menjelaskan kecenderungan umat beragama kita yang lebih mengutamakan aspek “ritual keagamaan” yang bersifat formalis- simbolik daripada aspek “pengetahuan” yang bersifat substantif. Ada problem literasi keagamaan, menurut Halim, sehingga umat beragama kita menampilkan wajah paradoks, yang kemudian diistilahkan dalam judul bukunya, “Taat Ritual, Tuna Sosial” (2022).
Hanya saja, literasi keagamaan yang diupayakan bukan hanya dengan “belajar agama” seperti yang berjalan sejauh ini, melainkan juga dengan “belajar tentang agama”, ujarnya meminjam pendapat Mun’im Sirry (2019), bahkan dia sendiri menggagas diperlukan juga “belajar beragama”. “Belajar agama” sejauh ini dianggap hanya sebatas memberikan pemahaman doktrinal kepada umat beragama. Misalnya, pengetahuan tentang Rukun Islam. Hanya saja, seringkali itu hanya diterima sebagai doktrin dan belum dipahami secara komprehensif. Sebagian umat Islam belum memahami hikmah dari ketentuan syari’at (hikmat at-tasyri’) tentang Rukun Islam. Di sinilah Mun’im Sirry menawarkan konsep “belajar tentang agama”.
Namun demikian, Wahyuddin Halim (2022) menganggap belum cukup sampai di situ, diperlukan juga “belajar beragama”, yaitu upaya beragama yang dibiasakan umat sejak dini dan dari tingkat keluarga sebagai lingkungan sosial terkecil masyarakat. Menurut Halim, nilai-nilai agama tidak tercermin dalam realitas sosial umat beragama, karena sebagian di antaranya tidak membiasakan dan mempraktekkan nilai-nilai tersebut sejak dini, yang dalam antropologi disebut sebagai “habitus”.
Syari’at tentang Puasa Ramadhan misalnya, semestinya tidak hanya dipahami sebatas menahan lapar dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, melainkan juga mengajarkan tentang sikap pengendalian diri untuk tidak merugikan apalagi menyakiti orang lain serta sikap solidaritas sosial untuk saling berbagi. Prinsip nilai tentang pengendalian diri dan solidaritas sosial itu semestinya tidak hanya berhenti saat puasa tetapi juga di luar puasa, tidak hanya pada ritualnya tetapi juga pada perilakunya. Namun pada kenyataannya, umat kita masih terjebak pada kondisi yang taat secara ritual tapi tuna secara sosial itu. Sebagian besar umat beragama kita memang rajin berpuasa, tetapi dalam praktik hidupnya masih jauh dari perbuatan yang membuat aman orang lain dan peduli secara sosial.
Gagasan ini menarik untuk menjadi solusi kesalehan sosial kita ke depan. Para pelaku dakwah dan pendidik keagamaan, bahkan semua umat beragama, harus mulai berbenah dalam pembelajaran keagamaan umat kita. Pembelajaran agama yang tidak hanya memberikan “pelajaran agama”, tetapi juga “pelajaran tentang agama” dan “pelajaran beragama”. (Edijun)