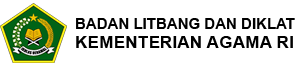Makna Rajinnya Berdoa dalam Konteks Kualitas SDM: Menakar Religiusitas dan Daya Saing Global

80 tahun peringatan proklamasi Indonesia, dan sampai sekarang sering dijuluki sebagai negara religius. Enam hari terakhir, data dari HouseFresh sebagaimana dilansir oleh CNBC Indonesia (2025) menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat pertama dalam hal intensitas doa menjadi perbincangan menarik. Menurut data ini dalam sehari, warga Indonesia rata-rata melakukan doa hingga 12 kali, mengungguli negara-negara seperti Arab Saudi, India, bahkan Iran. Predikat ini diperkuat oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak di dunia, sebagaimana diungkap dalam laporan Kementerian Agama (2025), yang menyatakan bahwa kuota haji Indonesia mencapai 221.000 orang. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, fakta ini tidaklah mengherankan. Namun, ketika religiusitas ini dikaitkan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) dan daya saing ekonomi, Indonesia justru tertinggal.
Menurut laporan World Competitiveness Ranking (2025), kita bisa melihat bahwa posisi daya saing Indonesia turun drastis ke peringkat 40 dari 67 negara. Di kawasan ASEAN, Indonesia bahkan hanya lebih unggul dari Thailand dan Filipina, tertinggal dari Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Hal ini menjadi kontras yang mencolok: di satu sisi masyarakat sangat religius, namun di sisi lain kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing global belum optimal. Lantas, apa makna rajinnya berdoa bila tidak berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup dan daya saing bangsa? Apakah religiusitas hanya bersifat ritualistik tanpa muatan transformasi sosial dan peningkatan kapasitas individu?
Dengan demikian, kita bisa berasumsi bahwa tingginya intensitas aktivitas keagamaan belum tentu berbanding lurus dengan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun produktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, religiusitas di Indonesia cenderung bersifat simbolik dan ritualistik, tanpa pemaknaan fungsional yang menumbuhkan nilai-nilai produktif. Di sisi lain, negara-negara seperti Singapura dan Amerika Serikat yang berada di peringkat bawah dalam indeks religiusitas justru menempati posisi teratas dalam hal daya saing dan kualitas SDM.
Harapannya, religiusitas yang produktif sejatinya bukan sekadar tentang banyaknya ritual, tetapi bagaimana nilai-nilai agama membentuk etos kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, dan inovasi. Dalam Islam, misalnya, nilai-nilai seperti itqan (perfeksionisme dalam bekerja), amanah (tanggung jawab), dan ikhlas (ketulusan dalam berkarya) menjadi fondasi bagi pembangunan SDM yang unggul. Sayangnya, nilai-nilai luhur ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sosial dan budaya kerja masyarakat Indonesia.
Agama Berdampak: Gagasan Progresif Kementerian Agama
Menteri Agama RI, melalui berbagai kebijakan strategisnya mendorong transformasi pemahaman dan praktik beragama yang berdampak. Gagasan “Agama Berdampak” yang diusung menjadi pengingat bahwa keberagamaan harus mendorong perubahan sosial, bukan hanya mempertahankan status quo ritualistik. Agama bukan sekadar urusan privat dengan Tuhan, tetapi memiliki dimensi sosial yang luas, termasuk pembangunan manusia dan kesejahteraan publik.
Konsep ini menemukan pijakan kuat dalam visi moderasi beragama, yang telah menjadi arus utama (mainstreaming) kebijakan Kementerian Agama sejak 6 tahun terakhir. Melalui Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM (BMBPSDM), Kemenag berupaya menjembatani kesenjangan antara pemahaman keagamaan yang sering eksklusif dan realitas sosial yang membutuhkan kolaborasi dan keterbukaan. Moderasi bukanlah peminggiran agama, melainkan pemaknaan ulang agar agama tetap relevan dan solutif dalam konteks kekinian.
Moderasi beragama pada dasarnya mengandung nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, keseimbangan, dan musyawarah. Nilai-nilai ini tidak hanya penting untuk menjaga harmoni sosial, tetapi juga menjadi basis penting dalam pengembangan SDM yang kompetitif secara global. Ketika seseorang mampu bersikap moderat, ia cenderung memiliki keterampilan berpikir kritis, empati sosial, dan kemampuan komunikasi yang baik --semua ini adalah kompetensi inti dalam era ekonomi berbasis pengetahuan.
BMBPSDM Kemenag memiliki peran strategis dalam menyinergikan nilai-nilai religiusitas dengan penguatan kapasitas individu dan kelembagaan. Misalnya, pelatihan ASN berbasis moderasi beragama tidak hanya mengajarkan toleransi, tetapi juga membentuk integritas, profesionalisme, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan ekosistem birokrasi yang lebih humanis, efektif, dan inovatif.
Religiusitas sebagai Energi Sosial dan Ekonomi
Rajinnya berdoa seharusnya tidak menjadi penghalang produktivitas, namun menjadi penyemangat untuk bekerja lebih giat, berbuat lebih jujur, dan bersikap lebih adil. Dalam Islam, doa bukan sekadar permintaan, tetapi ekspresi harapan dan niat untuk berbuat. Doa semestinya menjadi energi psiko-spiritual yang menggerakkan kerja, bukan pengganti kerja.
Negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan mungkin tidak religius dalam pengertian konvensional, namun mereka memiliki etos kolektif yang mirip dengan nilai-nilai spiritualitas: kerja keras, tanggung jawab sosial, dan dedikasi. Di sinilah peran penting Kementerian Agama --termasuk melalui program-program peningkatan literasi keagamaan transformatif --untuk memastikan bahwa ajaran agama tidak berhenti di mimbar, tetapi hidup dalam tindakan dan kontribusi nyata di masyarakat.
Dalam konteks sosial, tingginya aktivitas keagamaan belum juga mereduksi tindakan-tindakan intoleran. Kasus penolakan dan perusakan rumah doa di Padang dan Cidahu, Sukabumi, menunjukkan masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama yang penuh kasih sayang dan cinta damai. Padahal semua agama mengajarkan cinta sebagai fondasi hubungan antar manusia dan Tuhan.
Konsep agama cinta (religion of love) perlu digaungkan lebih kuat oleh Kementerian Agama, baik melalui pendidikan agama formal maupun nonformal. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin menekankan kasih sayang universal, bukan kekerasan atau penolakan terhadap yang berbeda. Menghidupkan konsep agama cinta juga berarti memperkuat toleransi, solidaritas sosial, dan kemampuan berelasi secara sehat di tengah masyarakat majemuk.
Pendidikan agama yang menekankan cinta dan etika sosial, bukan hanya doktrin ritual, akan melahirkan generasi beragama yang lebih bijak, terbuka, dan peduli. Inilah jenis SDM unggul yang dibutuhkan Indonesia --bukan hanya pintar, tetapi juga berhati nurani.
Indonesia memiliki modal spiritual yang besar, namun belum cukup digunakan sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berdaya saing. Dibutuhkan integrasi yang kuat antara religiusitas dan penguatan kapasitas individu. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan pendidikan berbasis nilai, pelatihan kompetensi berbasis etika keagamaan, serta reformasi birokrasi berbasis akhlak mulia.
Kementerian Agama dapat menjadi pelopor integrasi ini melalui transformasi pendidikan madrasah, pesantren, dan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Penekanan pada nilai integritas, kolaborasi, inovasi, dan kecintaan terhadap ilmu harus menjadi ruh dari seluruh proses pendidikan keagamaan. Dengan begitu, keberagamaan bukanlah sekadar simbol, tetapi jalan menuju SDM unggul yang berkontribusi secara nyata pada pembangunan nasional dan global.
Rajinnya berdoa bukanlah indikator utama keberhasilan suatu bangsa, melainkan bagaimana doa itu menjelma menjadi aksi, etika, dan kebijakan. Religiusitas harus menjadi sumber kekuatan untuk memperbaiki kualitas hidup, bukan hanya perhiasan statistik.
Kementerian Agama, melalui gagasan “Agama Berdampak” dan penguatan moderasi beragama, memiliki peran sentral dalam membumikan nilai-nilai agama agar menyatu dengan kerja-kerja sosial dan peningkatan SDM. Dengan religiusitas yang tercerahkan, penuh cinta, dan berdampak sosial, Indonesia bisa membalikkan paradoks: menjadi bangsa yang tidak hanya rajin berdoa, tetapi juga unggul dalam daya saing dan kualitas manusia. (Firman Nugraha, widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Bandung)