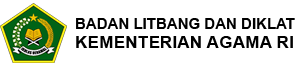MUI 50 Tahun: Penengah Umat di Era Polarisasi Digital

Jakarta (BMBPSDM)---Pada 26 Juli 2025, Majelis Ulama Indonesia (MUI) genap berusia 50 tahun. Setengah abad merupakan waktu yang tidak singkat bagi sebuah lembaga untuk tetap relevan dan dipercaya publik. Milad ke-50 MUI yang mengusung tema “MUI Berkhidmat untuk Kemaslahatan Umat dan Keharmonisan Bangsa” menjadi momentum penting, tidak hanya untuk refleksi, tetapi juga untuk meneguhkan komitmen dalam merespons dinamika zaman.
Sejak didirikan pada 1975, MUI telah menjadi rumah besar bagi berbagai organisasi Islam di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya dikenal karena fatwa halal atau haram, melainkan juga memainkan peran sebagai penengah dalam perbedaan pandangan keagamaan, serta sebagai jembatan antara umat Islam dan pemerintah.
Namun, di era transformasi digital saat ini, MUI dituntut untuk lebih aktif hadir di media sosial. Masyarakat tidak lagi menunggu ceramah di masjid atau majelis pengajian untuk mencari jawaban atas persoalan keagamaan. Banyak di antara mereka yang mencarinya langsung melalui Google atau media sosial.
Di sinilah posisi strategis MUI diuji, agar perbedaan pandangan fikih tidak berkembang menjadi konflik sosial. Selama ini, fatwa-fatwa MUI bersifat wasathiyah (moderat) dan mengutamakan kemaslahatan umat. Dalam isu vaksin COVID-19, misalnya, MUI tidak serta-merta mengeluarkan vonis halal atau haram tanpa mempertimbangkan kondisi darurat, kesehatan masyarakat, dan keselamatan bersama.
Polarisasi di Era Digital
Dewasa ini, polarisasi di tengah masyarakat sering kali dipicu oleh narasi ekstrem di media sosial. Siapa pun dapat dengan mudah menyebarkan opini tanpa verifikasi, seolah-olah ruang digital merupakan arena bebas tanpa konsekuensi. Tidak jarang, dalil agama digunakan untuk membenarkan kebencian dan kekerasan verbal.
Media sosial yang pada awalnya dipandang sebagai ruang demokratisasi gagasan, kini sering kali berubah menjadi medan pertempuran wacana yang dipenuhi dengan nada kebencian. Orang lebih cepat melabeli orang lain sebagai kafir daripada berusaha memahami perbedaan. Ujaran kebencian kerap dibenarkan atas nama amar ma’ruf nahi munkar, padahal substansinya sering kali hanya merupakan pelampiasan kebencian pribadi yang dibungkus dengan retorika keagamaan.
Menanggapi situasi tersebut, pada 2017 MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 24 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Fatwa ini menegaskan bahwa menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, fitnah, dan permusuhan melalui media sosial adalah perbuatan haram. Larangan tersebut tidak hanya bernilai doktrinal secara keagamaan, tetapi juga menjadi panggilan moral agar ruang digital tidak berubah menjadi sarang kebencian dan perpecahan.
Selain melalui fatwa, MUI juga memiliki legitimasi untuk melakukan tabayyun dan klarifikasi terhadap konten keagamaan yang menyesatkan. Dengan pendekatan ilmiah dan otoritas keulamaan, MUI membimbing umat dalam membedakan antara konten keagamaan yang sahih dan yang sekadar bersifat provokatif demi kepentingan tertentu. Tanggung jawab ini tentu menuntut kecepatan dan kehadiran digital yang aktif, agar umat tidak terlanjur termakan narasi sesat sebelum memperoleh rujukan yang otoritatif.
Ruang digital memerlukan kehadiran otoritas moral yang menyejukkan, bukan yang menakut-nakuti. Media sosial menuntut semua pihak --terutama para pemuka agama-- untuk bijak memilih kata, menahan jari sebelum menekan tombol bagikan, serta mempertimbangkan maslahat dan mafsadat dari setiap kalimat yang ditulis. Polarisasi akan terus berkembang jika tidak ada peneguhan nilai-nilai kebaikan bersama.
Menjadi Penengah di Era Digital
Informasi keagamaan kini tersebar luas di media sosial, YouTube, TikTok, dan berbagai platform digital tanpa filter otoritatif. Ada pendakwah yang menyejukkan, tetapi tidak sedikit pula yang memicu kontroversi, kebencian, dan kesalahpahaman dalam beragama. Fenomena dakwah berbasis clickbait demi viralitas juga rawan menimbulkan konflik horizontal.
Sebagai lembaga yang menaungi berbagai organisasi masyarakat Islam, MUI merepresentasikan keberagaman pemikiran Islam di Indonesia --dari yang tradisional hingga modernis. Keberagaman ini merupakan modal penting untuk meneguhkan wajah Islam Indonesia yang wasathiyah, inklusif, dan toleran.
Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah meningkatkan literasi digital para ulama muda. Mereka memiliki kapasitas keilmuan keagamaan yang mendalam, tetapi belum semuanya menguasai komunikasi digital yang efektif, kreatif, dan menyejukkan.
Sementara itu, algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sensasional dan ekstrem, sehingga pesan Islam moderat sering kali tenggelam. Padahal, media sosial memungkinkan audiens untuk berinteraksi secara langsung, yang membuka ruang dialog partisipatif dan dinamis (Fandy, 2014).
Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M. Cholil Nafis, menyatakan bahwa di tengah maraknya ajaran yang menyimpang di media sosial, para dai perlu aktif menyampaikan pendapat agar masyarakat lebih selektif dalam menerima dakwah. Jika menjumpai konten yang menyesatkan, para dai diimbau untuk memberikan komentar dan klarifikasi (MUI.or.id, 2024).
Kita lahir dengan keragaman suku, agama, mazhab, dan tradisi. Tanpa kehadiran lembaga seperti MUI, suara keagamaan berisiko terfragmentasi tanpa arah yang jelas, bahkan dapat menimbulkan konflik tafsir dan ideologi yang membahayakan persatuan nasional. MUI selama ini hadir sebagai penyejuk di tengah silang pendapat dan potensi polarisasi keagamaan yang menguat.
Ruang digital tidak boleh dibiarkan kosong dari nilai-nilai keislaman yang sejuk dan mencerahkan. Para ulama muda perlu didampingi agar tidak hanya mahir dalam ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga terampil menjadi komunikator efektif di ruang digital. Dengan demikian, wajah Islam Indonesia akan tetap teduh dan moderat.
Setengah abad perjalanan MUI menunjukkan bahwa bangsa ini membutuhkan lembaga ulama yang mampu menavigasi dinamika zaman tanpa kehilangan prinsip dasar ajaran Islam. Milad ke-50 bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk meneguhkan komitmen MUI dalam berkhidmat bagi umat dan bangsa.