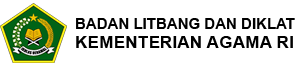Membangun SDM Unggul melalui Pengembangan Kompetensi yang Adaptif dan Berkelanjutan

Garut (BMBPSDM)---Dalam lima tahun terakhir, dunia pelatihan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi (bangkom) sumber daya manusia (SDM) menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi, perubahan pola kerja, dan tuntutan kompetensi baru menuntut penyelenggara pelatihan untuk terus berinovasi. Kegiatan pengembangan kualitas tenaga pelatihan yang baru-baru ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi SDM dan Penguatan Karakter (Pusbangkom SDMPK) di Garut (7–9 Mei 2025) menjadi contoh nyata upaya serius dalam menjawab tantangan tersebut. Namun, di balik kegiatan formal, ada beberapa prinsip mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama.
Salah satu poin krusial dalam bangkom SDM adalah perlunya bergerak melampaui sekadar pemenuhan standar. Jangan sampai penyelenggaraan pelatihan terjebak dalam paradigma conformity yakni memastikan peserta mencapai kompetensi minimum yang ditetapkan. Padahal, tuntutan zaman sekarang menuntut pendekatan beyond standard, di mana peserta didorong untuk mencapai kapasitas terbaiknya.
Konsep ini sejalan dengan tuntutan dunia modern yang menekankan tiga hal: better (lebih baik), faster (lebih cepat), dan cheaper (lebih efisien). Dalam konteks bangkom aparatur sipil negara (ASN), ini berarti tidak hanya sekadar mengejar sertifikasi, tetapi membangun pola pikir pembelajar sepanjang hayat.
Pelatihan sebagai Medium Pewarisan Ilmu dan Peradaban
Manusia, sebagai makhluk berpikir (cogito ergo sum), memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu bukan sekadar kumpulan teori, melainkan warisan peradaban yang harus ditransmisikan antargenerasi. Dalam konteks ini, pelatihan seharusnya menjadi medium strategis untuk mempercepat proses transmisi pengetahuan sekaligus mengadaptasikannya dengan kebutuhan zaman.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan pelatihan yang dalam pelaksanaannya terjebak pada pendekatan satu arah (teacher-centered), padahal partisipasi aktif peserta (learner-centered) jauh lebih efektif. Pendekatan heutagogi (pembelajaran mandiri) seharusnya mulai diintegrasikan dalam pelatihan, terutama untuk peserta dewasa yang sudah memiliki pengalaman kerja. Sayangnya, perubahan metode ini masih berjalan lambat karena keterbatasan kesiapan fasilitator dan budaya belajar yang belum terbentuk.
Kita bisa belajar dari Darwin yang mengingatkan bahwa mereka yang bertahan bukanlah yang terkuat, melainkan yang paling adaptif. Prinsip ini sangat relevan dalam dunia pelatihan. Jika lembaga pelatihan dan widyaiswara tidak mampu beradaptasi dengan perubahan baik dalam hal teknologi, metodologi, maupun kebutuhan peserta, maka keberadaannya akan tergantikan oleh platform digital yang lebih fleksibel.
Talcott Parsons melalui teori AGIL (adaptation, goal attainment, integration, latency) menjelaskan bahwa adaptasi adalah langkah pertama dalam perubahan sosial. Artinya, sebelum mencapai tujuan besar, sebuah organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam konteks pelatihan, ini berarti lembaga pelatihan harus peka terhadap tren terkini, seperti penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence), microlearning, atau gamification. Namun, adaptasi tidak boleh sekadar ikut-ikutan tren, melainkan harus disertai dengan integrasi yang matang agar tidak kehilangan esensi pelatihan itu sendiri.
Tantangan Nyata yang Harus Dijawab
Beberapa tantangan konkret yang dihadapi dunia pelatihan saat ini antara lain adanya disrupsi teknologi versus keterbatasan infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan paradoks: di satu sisi, teknologi menawarkan solusi pelatihan daring yang fleksibel; di sisi lain, tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang memadai. Banyak ASN, terutama di daerah terpencil, masih kesulitan mengakses pelatihan berbasis digital.
Kesenjangan jumlah dan kompetensi fasilitator juga merupakan tantangan penting. Widyaiswara atau tenaga pelatihan harus terus didorong agar terbiasa dengan metode pembelajaran modern. Pusbangkom perlu meningkatkan jumlah dan kualitas pelatihan untuk fasilitator (training of trainers) yang berorientasi pada penguatan kapasitas mendalam.
Tantangan terakhir adalah paradigma antara kuantitas versus kualitas peserta. Tidak disangkal bahwa masih ada orientasi pada target jumlah peserta yang sering kali lebih diutamakan daripada kedalaman materi. Contoh nyata, seperti yang dilaporkan Muhtadin, Kepala Bagian Tata Usaha Pusbangkom SDMPK, bahwa dari 3,1 juta ASN Kementerian Agama, baru 1,8 juta yang terlayani. Padahal, yang tidak kalah penting adalah memastikan pelatihan benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja.
Stephen R. Covey dalam The 7 Habits of Highly Effective People menekankan pentingnya kebiasaan (habit) dalam mencapai kesuksesan. Prinsip ini sangat relevan dalam pelatihan. Jika peserta hanya datang, duduk, mendengar, lalu pulang tanpa internalisasi, maka pelatihan tersebut sia-sia.
Oleh karena itu, pelatihan harus dirancang untuk mendorong refleksi kritis, bukan sekadar transfer pengetahuan. Pelatihan juga didesain agar dapat memicu lahirnya aksi nyata, seperti proyek aplikatif setelah pelatihan. Terakhir, upaya bangkom harus dibarengi dengan membangun komunitas belajar agar proses pembelajaran terus berlanjut meskipun pelatihan telah selesai.
Apa yang dilakukan Pusbangkom SDMPK patut diapresiasi, tetapi ini baru langkah awal. Pelatihan harus dilihat sebagai gerakan berkelanjutan untuk membangun budaya belajar di kalangan ASN. Tanpa komitmen bersama dari penyelenggara, fasilitator, hingga peserta pelatihan hanya akan menjadi ritual tahunan tanpa makna.
Seperti kata Ali bin Abi Thalib, “Ilmu tanpa amal adalah omong kosong, amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan.” Pelatihan yang berkualitas harus melahirkan bukan hanya manusia terlatih, tetapi juga manusia yang terus belajar, beradaptasi, dan berkontribusi pada perubahan positif.
(Disklaimer: Tulisan diadaptasi dari paparan Kepala BMBPSDM dalam kegiatan Pusbangkom SDMPK, 7–9 Mei 2025.)
Firman Nugraha