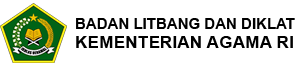Nilai-Nilai Universal Agama

Oleh: Abdul Jalil
Widyaiswara Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan
Jakarta (24 Oktober 2021). Dalam bingkai paradigma nasional, motto Bhineka Tunggal Ika harus mengkristal ke semua umat beragama, sehingga menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma kebersamaan (shared norm) dalam realitas keragaman menjadi landasan utama bagi terbangunnya kerukunan sosial yang tulus dan permanen. Upaya memahami agama orang lain merupakan hal paling mendasar yang harus ada dalam relasi kehidupan keberagamaan di Indonesia.
Saling bekerjasama antar penganut dan kelompok agama merupakan puncak dari sikap saling mengakui dan saling menghormati antar pemeluk agama. Keharmonisan kehidupan umat beragama yang sejati akan terlihat dari adanya kesamaan keprihatinan (concern) dan kepentingan yang terwujud dalam tujuan serta aktivitas kolektif yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Pada hakikatnya semua agama mengajarkan perdamaian (peace), dan tidak membenarkan kekerasan. Namun demikian, realitasnya tidak sedikit terjadi aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Salah satu alasan mengapa agama begitu mudah dilekatkan dengan kekerasan, barangkali karena setiap agama memiliki klaim kebenaran dan misi untuk menegakkan kebenaran tersebut. Sementara itu, banyak penganut agama yang masih menyalahpahami perdamaian dan nirkekerasan sebagai kompromi dan kepasifan yang berlawanan dengan misi tersebut. Damai dan konflik adalah dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Terjadinya suasana damai hari ini belum tentu menghapuskan secara radikal benih konflik, karena konflik dapat muncul kembali ke permukaan yang disebabkan faktor internal maupun eksternal.
Agama memang dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua, di satu sisi ia dapat menjadi perekat dan pemersatu bagi umat, namun di sisi lain ia juga dapat menjadi pemicu konflik dalam masyarakat, hal ini tergantung cara memahaminya. Faktanya, konflik umat beragama seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan agama yang tidak disikapi dengan rasa tasamuh (toleransi) dari masing-masing penganut agama. Masing-masing merasa menjadi pemegang kebenaran yang berimplikasi bahwa orang lain dianggap salah. Seharusnya, meyakini suatu agama sebagai “kebenaran absolut” tidak harus dijadikan legitimasi untuk menyalahkan orang lain.
Dilema agama-agama yang paling serius adalah tatkala berhubungan dengan kalangan di luar komunitasnya. Hampir semua agama memandang pihak lain lebih rendah, bahkan cenderung mendiskreditkan ketika berbicara komunitas di luar dirinya. Tantangan yang dihadapi umat beragama dewasa ini adalah menjalankan misi keagamaan tanpa menimbulkan benturan dan kerusakan, melainkan membawa kemaslahatan; menebarkan kebaikan kepada semua kalangan, tanpa mengkompromikan keyakinan, tetapi justru memperkokohnya.
Agama Sebagai Pendorong Perdamaian
Agama seringkali dihubungkan dengan kekerasan, terlebih setelah serangan terorisme di Amerika Serikat pada 2001, dan serangan teror lain di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam merespons stigma media Barat bahwa “agama adalah sumber terorisme”, para pemuka agama cenderung mencari-cari dalil agama yang mengecam tindakan terorisme. Padahal yang diperlukan adalah menunjukkan dimensi dari agama yang mengandung nilai dan landasan bagi bina damai yang menunjukkan agama tidak pasif, melainkan secara aktif turut andil dalam mendorong perubahan di masyarakat. Alissa Wahid menyebutkan, cara lama merespons konflik yang sering dilakukan para tokoh dan pemerintah adalah “deklarasi”.
Selama ini, damai seringkali hanya dimaknai secara sempit sebagai ketenangan, keselamatan, kepasrahan, dan bahkan kompromi. Perdamaian juga umumnya dipahami sebagai gencatan senjata atau perjanjian mengakhiri pertikaian. Padahal perdamaian yang hakiki tidak hanya mensyaratkan tiadanya kekerasan langsung, tetapi juga sirnanya kekerasan yang lebih luas pada tataran sistem dan budaya. Agama memiliki peran sangat penting, karena menjadi salah satu unsur yang dapat membangun etika sosial, sistem, dan budaya masyarakat. Dalam aspek doktrin keagamaan, semua agama mengajarkan agar penganutnya menciptakan dan memelihara kedamaian. Maraknya konflik dan kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah, disebabkan antara lain oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman sebagian umat beragama terhadap ajaran agama lain, di samping agamanya sendiri. Keadaan demikian menyebabkan umat beragama yang bersangkutan mempunyai pandangan keagamaan yang sempit dan eksklusif. Akibatnya mudah menyalahkan orang lain.
Prasyarat untuk menuju terwujudnya perdamaian harus didasarkan pada adanya komunikasi yang berlangsung secara jujur dan terbuka, sehingga diketahui kesulitan dari masing-masing pihak. Dialog adalah upaya menjembatani benturan, namun dialog tidak hanya berhenti dalam tataran perbincangan atau wacana semata. Karena itu, perlu tindakan nyata sebagai manifestasi dari pencarian resolusi atas sebuah konflik. Konsep bina damai (peace building) pertama kali dipopulerkan oleh Bhoutros-Bhoutras Ghali, mantan Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 1992, dan diperkuat oleh paparan John Galtung dan Andi Knight. John Galtung menyatakan bahwa peace building adalah proses pembentukan perdamaian yang tertuju pada implementasi praktis perubahan sosial secara damai melalui rekonstruksi dan pembangunan politik, sosial, dan ekonomi.
Dalam pemetaan konflik, Galtung memperkenalkan konsep segitiga konflik dan perbedaan antara kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan budaya, serta memperkenalkan antara perdamaian negatif dan perdamaian positif. Peace building bagi Galtung lebih menekankan pada proses jangka panjang, penelusuran dan penyelesaian akar konflik, mengubah asumsi-asumsi yang kontradiktif, serta memperkuat elemen yang dapat menghubungkan pihak-pihak yang bertikai dalam suatu formasi baru demi mencapai perdamaian positif. Andi Knight, ilmuwan politik Kanada dalam bukunya Building Sustainable Peace, menyatakan peace building terkait dengan dua hal esensial, yaitu dekonstruksi struktur kekerasan dan merekonstruksi struktur perdamaian. Tujuan utamanya adalah mencegah atau menyelesaikan konfik serta menciptakan situasi damai melalui transformasi kultur kekerasan menjadi kultur damai.
Hubungan antar umat beragama di Indonesia kerap terganggu oleh serangkaian konflik bernuansa kekerasan (violent conflict) yang banyak terjadi di beberapa daerah. Beberapa konflik keagamaan yang menjadi isu nasional antara lain: konflik komunal Muslim-Kristen di Poso (1989 -2006), konflik Muslim-Kristen di Ambon (1999-2002), konflik Gereja Yasmin di Bogor (2008), konflik Gereja HKBP Filadelpia di Bekasi (2009), penyerangan pengikut Ahmadiyah di Cikeusik (2011), konflik penyerangan penganut Syi’ah di Sampang (2012), konflik pembakaran masjid di Tolikara Papua (2015), konflik pembakaran gereja di Aceh Singkil (2015), konflik pembakaran vihara di Tanjung Balai (2016), dan pengusiran warga Ahmadiyah di Desa Greneng Lombok Timur (2018). Meskipun secara ideal normatif tidak ada agama yang mengajarkan konflik dan permusuhan, tetapi secara faktual-historis sikap intoleran, primordialisme, dan radikalisme menjadi bagian dari penyebab atau sumber konflik. Di sini letak salah satu urgensi mengapa pengarusutamaan (mainstreaming) budaya damai perlu dilakukan bagi semua pihak terkait. Para tokoh agama berperan untuk mengartikulasikan pemahaman keagamaan yang moderat dan sejuk, serta mendorong lahirnya sikap masyarakat pemeluk agama yang saling menghormati terhadap pemeluk agama lain.