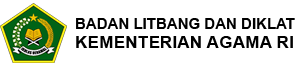Perkembangan Islam Liberal di Indonesia

-
Kamis, 30 Juni 2011
Perkembangan Islam Liberal di Indonesia
M. Atho Mudzhar
Kepala Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI
Gd. Bayt Al-Qur’an Komplek
TMII Jakarta
Abstract
In the 1990’s, a group of young people that call themselves ‘Liberal Islam’ tried to give response toward issues that occurred in the 20th century. Indonesian Ulama Council (Majelis Ulama Indonesia) foresees the potential dangerbrought by the ideas from this group. IN 2005, MUI had
produced a fatwa which stated that pluralism, secularism, and liberalism are concepts that violate Islamic teachings.
Implementing and believing those concepts are haram for Muslims.This liberal group emphasizes on personal freedom and liberation toward socio-political structure. Liberalism is an interpretation attempt upon nash with a hermeneutical approach as its base. With that approach,this group understands that: a) ijtihad is open for all dimensions, (b)the religio-ethical spirit is more important than literate text definitions, c) The openness relative truth (relativitism) and plural are more important, d) Minorities and the suppressed should be granted advocacy. e) Religion and faith is a form of freedom f) World authority should be separated by ukhrowi authority, between religious authority and politics. The Liberal Islam in Indonesia emphasizes in: 1) Conveying the jihad spirit, 2)Conveying rationalism, 3) Upholding Democratic values,4) Upholding the role of science and education. 5)Perceiving that "Islamic Nation" is a harmful shift of attraction, 6) Accepting and supporting the society’s pluralism, 7) Embracing Humanitarianism principals, and perceiving it as the essence and heart of Islam, 8) Striving for gender equality
Keyword:
Hermeneutical tafsir (interpretation), relativism, pluralism, fatwa
Pendahuluan
Istilah Islam liberal tadinya tidak terlalu dikenal dan diperhatikan orang di Indonesia. Apalagi jumlah pendukungnya amat kecil, dapat dihitung dengan jari. Istilah itu justru menjadi amat populer setelah dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonsia (MUI) pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa faham liberalisme adalah sesat dan menganut faham itu adalah haram hukumnya. Jadi, terlepas dari perdebatan tentang keabsahan fatwa itu, istilah Islam liberal di Indonesia justru dipopulerkan oleh pihak penentangnya. Memang terkadang suara merekapun nyaring bunyinya.
Arti kata Islam liberal tidak selamanya jelas. Leonard Binder, seorang guru besar UCLA, ketika menulis buku berjudul Islamic Liberalism (University of Chicago Press, 1988) memberinya arti "Islamic political liberalism" dengan penerapannya pada negara-negara Muslim di Timur Tengah. Mungkin di luar dugaan sebagian orang, buku itu selain menyajikan pendapat Ali Abd Raziq (Mesir) yang memang liberal karena tidak melihat adanya konsep atau anjuran negara Islam, tetapi juga membahas pikiran Maududi (Pakistan) yang tentu saja lebih tepat disebut sebagai tokoh fundamentalis atau revivalis.
Sebaliknya bagi Greg Barton, dalam bukunya berjudul Gagasan Islam Liberal di Indonesia(Penerbit Paramadina, Jakarta, 1999) istilah "Islamic liberalism" nampaknya cukup jelas. Dalam bukunya yang berasal dari disertasi itu ia mengatakan bahwa Islam liberal di Indonesia adalah sama dengan pembaruan Islam atau Islam neo-modernis. Selanjutnya, dalam penelitian yang mengcover periode 1968-1980 itu, Barton membatasi diri pada pemikiran empat orang tokoh dari kaum neo-modernis, yaitu Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid.
Seperti diketahui, istilah neo-modernis berasal dari Fazlur Rahman, seorang tokoh neo-modernis muslim asal Pakistan yang terakhir menjadi Guru Besar studi keislaman di Universitas Chicago. Fazlur Rahman,sebagaimana dikutip Greg Barton, membedakan gerakan pembaruan Islam dalam dua abad terakhir kepada empat macam, yaitu: revivalisme Islam, modernisme Islam, neo-revivalisme Islam, dan neo-modernisme Islam.
Dengan revivalisme Islam dimaksudkan gerakan pada abad ke-18 yang diwakili oleh Wahhabiyyah di Arab, Sanusiyyah di Afrika Utara, dan Fulaniyyah di Afrika Barat. Sedangkan modernisme Islam di pelopori oleh Sayyid Ahmad Khan (W 1898) di India, Jamaluddin al-Afghani (W 1897) di Timur Tengah, dan Muhammad Abduh (W 1905) di Mesir. Adapun neo-revivalisme diwakili oleh Maududi dengan organisasinya yang terkenal, Jama’ati Islami, di Pakistan. Kemudian neo-modernisme Islam contohnya ialah Fazlur Rahman sendiri dengan karakteristik sintesis progresif dari rasionalitas modernis dengan ijtihad dan tradisi klasik (Greg Barton, 1999:9). Meskipun tipologi Fazlur Rahman ini dimaksudkan untuk seluruh dunia Islam, tetapi tipologi keempat diwakili juga oleh tokoh-tokoh Indonesia, khususnya empat orang yang disebutkan di atas.
Di Indonesia terdapat beberapa buku yang sering dinilai sebagai pendapat kelompok Islam liberal, dua diantaranya ialah buku Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Jakarta, 2005) yang ditulis oleh Tim Pengarusutamaan Gender pimpinan Musdah Mulia dan buku Fiqih Lintas Agama (Jakarta: Paramadina, 2004). Kalau kita cermati isi kedua buku itu terlihatlah bahwa banyak pendapat dan argumen di dalam kedua buku itu yang sama atau mungkin diambil dari pikiran-pikiran Muhammad Syahrur, seorang sarjana teknik Syria yang pernah belajar di Moskow, tetapi kemudian mengarang banyak buku tentang Islam, diantaranya yang terkenal ialah Nahw Ushûl Jadîdah fî al-Fiqh al-Islâmî yang telah diterbitkan juga dalam bahasa Indonesia dengan judul Metodologi Fiqih Islam Kontemporer (Yogyakarta: eLSAQ, 2004). Ini berarti bahwa pemikiran Islam liberal Indonesia bukanlah original, tetapi pengaruh literatur internasional. Apalagi Fazlur Rahman memang adalah guru Nurcholish Madjid dan mempunyai hubungan dengan kaum pemikir Islam Indonesia. Pemikir Timur Tengah lain yang mempunyai pengaruh terhadap pemikiran Islam liberal di Indonesia khususnya mengenai penggunaan hermeneutik untuk memahami Al Qur’an adalah Hamid Nasr Abu Zaid.
Islam Liberal di Indonesia (Era Orde Baru)
Sejak awal tahun 1970-an, bersamaan dengan munculnya Orde Baru yang memberikan tantangan tersendiri bagi umat Islam, beberapa cendekiawan Muslim mencoba memberikan respon terhadap situasi yang dinilai tidak memberi kebebasan berpikir. Kelompok inilah yang kemudian memunculkan ide-ide tentang "Pembaharuan Pemikiran Islam". Kelompok ini mencoba menafsirkan Islam tidak hanya secara tekstual tetapi justru lebih ke penafsiran kontekstual. Mereka dapat digolongkan sebagai Islam liberal dalam arti menolak taklid, menganjurkan ijtihad, serta menolak otoritas bahwa hanya individu atau kelompok tertentu yang berhak menafsirkan ajaran Islam.
Menurut Fachri Aly dan Bactiar Effendi (1986: 170-173) terdapat sedikitnya empat versi Islam liberal, yaitu modernisme, universalisme, sosialisme demokrasi, dan neo modernisme. Modernisme mengembangkan pola pemikiran yang menekankan pada aspek rasionalitas dan pembaruan pemikiran Islam sesuai dengan kondisi-kondisi modern. Tokoh-tokoh yang dianggap mewakili pemikiran modernisme antara lain Ahmad Syafii Ma‘arif, Nurcholish Madjid, dan Djohan Effendi. Adapun universalisme sesungguhnya merupakan pendukung modernisme yang secara spesifik berpendapat bahwa, pada dasarnya Islam itu bersifat universal. Betul bahwa Islam berada dalam konteks nasional, tetapi nasionalisasi itu bukanlah tujuan final Islam itu sendiri. Karena itu, pada dasarnya, mereka tidak mengenal dikotomi antara nasionalisme dan Islamisme. Keduanya saling menunjang. Masalah akan muncul kalau Islam yang me-nasional atau melokal itu menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap hakikat Islam yang bersifat universal. Pola pemikiran ini, secara samar-samar terlihat pada pemikiran Jalaluddin Rahmat, M. Amien Rais, A.M. Saefuddin, Endang Saefudin Anshari dan mungkin juga Imaduddin Abdul Rahim.
Pola pemikiran sosialisme–demokrasi menganggap bahwa kehadiran Islam harus memberi makna pada manusia. Untuk mencapai tujuan ini, Islam harus menjadi kekuatan yang mampu menjadi motivator secara terus menerus dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Para pendukung sosialis-demokrasi melihat bahwa struktur sosial politik dan, terutama, ekonomi di beberapa negara Islam termasuk Indonesia, masih belum mencerminkan makna kemanusiaan, sehingga dapat dikatakan belum Islami. Proses Islamisasi, dengan demikian, bukanlah sesuatu yang formalistik. Islamisasi dalam refleksi pemikiran mereka adalah karya-karya produktif yang berorientasi kepada perubahan-perubahan sosial ekonomi dan politik menuju terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis. Adi Sasono, M. Dawam Rahardjo, serta Kuntowidjojo dapat dimasukkan dalam pola pemikiran ini.
Sedangkan neo modernisme mempunyai asumsi dasar bahwa Islam harus dilibatkan dalam proses pergulatan modernisme. Bahkan kalau mungkin, Islam diharapkan menjadi leading ism (ajaran-ajaran yang memimpin) di masa depan. Namun demikian, hal itu tidak berarti menghilangkan tradisi keislaman yang telah mapan. Hal ini melahirkan postulat (dalil) al-muhâfazhat ‘alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhdu bi al-jadîd alashlah (memelihara tradisi lama yang baik, dan mengambil tradisi baru yang lebih baik). Pada sisi lain, pendukung neo modernisme cenderung meletakkan dasar-dasar keislaman dalam konteks atau lingkup nasional.
Mereka percaya bahwa betapapun, Islam bersifat universal, namun kondisikondisi suatu bangsa, secara tidak terelakkan, pasti berpengaruh terhadap Islam itu sendiri. Ada dua tokoh intelektual yang menjadi pendukung utama neo modernisme ini adalah Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid.
Tampaknya pemikiran Nurcholish (Prisma, nomor ekstra, 1984: 10-22), lebih dipengaruhi oleh ide Fazlur Rahman, gurunya di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Sedang pemikiran neo modernisme Abdurrahman Wahid telah dibentuk sejak awal karena ia dibesarkan dalam kultur ahlussunnah wal jama’ah versi Indonesia, kalangan NU. Karena itu, ide-ide keislamannya tampak jauh lebih empiris, terutama dalam pemikirannya tentang hubungan Islam dan politik. (Prisma, Nomor ekstra, 1984: 3-9; dan Prisma, 4 April 1984: 31-38).
Islam Liberal di Indonesia (Era Reformasi)
Sejak akhir tahun 1990an muncul kelompok-kelompok anak muda yang menamakan diri kelompok "Islam Liberal" yang mencoba memberikan respon terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul pada akhir abad ke- 20. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat betapa bahayanya pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh kelompok ini, sehingga pada Munasnya yang ke-7 pada tanggal 25-29 Juli 2005 mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme, sekularisme dan liberalism merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh sebab itu umat Islam haram hukumnya mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama (Adian Husaini, t.th: 2-4). Dalam Keputusan MUI No. 7/MUNAS VII/11/2005 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan liberalisme adalah memahami nash-nash agama (Al Qur’an dan As-Sunnah) menggunakan akal pikiran yang bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.
Islam liberal di Indonesia era reformasi nampak lebih nyata setelah didirikannya sebuah "jaringan" kelompok diskusi pada tanggal 8 Maret 2001, yang tujuannya adalah untuk kepentingan pencerahan dan pembebasan pemikiran Islam Indonesia. Usahanya dilakukan dengan membangun milis (islamliberal@yahoo.com). Kegiatan utama kelompok ini adalah berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam, negara, dan isu-isu kemasyarakatan. Menurut hasil diskusi yang dirilis pada tanggal 1 Maret 2002, Jaringan Islam Liberal (JIL) mengklaim telah berhasil menghadirkan 200 orang anggota diskusi yang berasal dari kalangan para penulis, intelektual dan para pengamat politik. Di antara mereka muncul nama-nama seperti; Taufik Adnan Amal, Rizal Mallarangeng, Denny JA, Eep Saefullah Fatah, Hadimulyo, Ulil Abshar-Abdalla, Saiful Muzani, Hamid Basyaib, Ade Armando dan Luthfi Assaukanie. Tentu tidak semua orang yang hadir diskusi berarti mendukung ide-ide JIL.
Diskusi awal yang diangkat oleh JIL adalah seputar definisi dan sikap Islam Liberal seputar isu-isu Islam, negara dan isu-isu kemasyarakatan. Pendefinisian Islam Liberal diawali dengan kajian terhadap buku Kurzman yang memilah tradisi keislaman dalam tiga kategori yakni, customary Islam, fundamentalis atau Wahabis atau Salafis, dan liberal Islam. Kategori ketiga diklaim sebagai koreksi dan respon terhadap dua kategori yang disebut pertama. Pertanyaan yang muncul dalam diskusi awal itu adalah apakah Islam Liberal di Indonesia akan bersifat elitis dan sekedar membangun wacana atau Islam Liberal yang menyediakan refleksi empiris, dan memiliki apresiasi terhadap realitas? Kalau Islam Liberal itu paralel dengan civicculture (pro pluralisme, equal opportunity, moderasi, trust, tolerance, memiliki sence of communityyang nasional, lalu di mana Islamnya? Atau Islam Liberal adalah skeptisisme dan agnostisme yang hidup dalam masyarakat Islam? Diskusi dalam milis yang panjang akhirnya tidak menyepakati sebuah definisi tentang Islam Liberal. Tetapi mereka menandai sebuah gerakan dan pemikiran yang mencoba memberikan respon terhadap kaum modernis, tradisional, dan fundamentalis.
Islam Liberal berkembang melalui media massa. Surat kabar utama yang menjadi corong pemikiran Islam Liberal adalah Jawa Pos yang terbit di Surabaya, Tempo di Jakarta dan Radio Kantor Berita 68 H, Utan Kayu Jakarta. Melalui media tersebut disebarkan gagasan-gagasan dan penafsiran liberal. Pernah suatu ketika, pemikiran dan gerakan ini menuai protes bahkan ancaman kekerasan dari lawan-lawan mereka. Bahkan masyarakat sekitar Utan Kayu pernah juga menuntut Radio dan komunitas JIL untuk pindah dari lingkungan tersebut. Karya-karya yang dicurigai sebagai representasi pemikiran liberal Islam dibicarakan dan dikutuk oleh lawanlawannya, terutama melalui khutbah dan pengajian. Buku seperti Fiqih Lintas Agama (Tim Penulis Paramadina), Menjadi Muslim Liberal (Ulil Abshar-Abdalla) Counter-Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Musda Mulia dkk), Indahnya Perkawinan Antar Jenis (Jurnal IAIN Walisongo) dan banyak lagi artikel tentang Islam yang mengikuti arus utama pemikiran liberal. Ketegangan antara yang pro dan kontra JIL, memuncak setelah keluarnya Fatwa MUI tentang haramnya liberalisme, sekularisme dan pluralisme pada tahun 2005. Ketegangan sedikit menurun setelah salah seorang contributor dan sekaligus kordinator JIL, Ulil Abshar-Abdalla pergi ke luar negeri, belajar ke Amerika Serikat.
Ulil melalui bukunya Menjadi Muslim Liberal menolak jenis-jenis tafsir keagamaan yang hegemonik, tidak pluralis, antidemokrasi, yang menurutnya potensial menggerogoti persendian Islam sendiri. Dengan gaya narasi dan semantik yang lugas, Ulil misalnya melancarkan kritiknya kepada MUI yang dalam pengamatannya telah memonopoli penafsiran atas Islam. Fatwa MUI yang menyatakan bahwa pluralisme, liberalisme, dan sekularisme adalah faham sesat; Ahmadiyah adalah keluar dari Islam – telah menyalakan emosi Ulil.
Pemikiran Ulil tidak bebas seratus persen. Sebagai alumni pesantren, ia tetap apresiatif terhadap keilmuan pesantren. Melalui kolomnya On Being Muslim kita tahu bahwa Ulil ternyata mendapatkan akar-akar liberalism pemikiran keislamannya juga dari ilmu-ilmu tradisional seperti ushûl alfiqh, qawâ‘id al-fiqhiyah yang dahulu diajarkan oleh para ustadznya di pesantren. Ilmu-ilmu pesantren semacam balaghah dan mantiq(logika) tampaknya turut melatih Ulil perihal bagaimana menstrukturkan kata dan kalimat, mensistematisasikan argumen serta mengukuhkan kekuatan dalam bernalar.
Sayangnya, hanya kalangan fundamentalis saja yang mencoba melakukan perlawanan retorik. Majalah seperti Sabili, Hidayatullah, dan media-media di lingkungan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mencoba untuk memberikan counter opini terhadap gagasan-gagasan yang diusung oleh JIL. Setelah Ulil pergi, dinamika pemikiran dan gerakan Islam kontemporer kembali adem ayem.
Profil Beberapa Kelompok Islam Liberal Di Indonesia
Jaringan Islam Liberal di Jakarta
Nong Darol Mahmada dan Burhanuddin dalam Imam Tholkhah dan Neng Dara Afiah (2005: 301-351) menjelaskan, JIL terbentuk pada tangal 9 Maret 2001. Tanggal tersebut merujuk pada awal diluncurkannya milis islamliberal@yahoogroups.com yang pada awalnya beranggotakan puluhan aktivis intelektual muda dari berbagai kelompok muslim moderat.
JIL berdiri antara lain karena kondisi sosial keagamaan pasca Orde Baru yang menurut para pendiri JIL dirasakan semakin menunjukkan wajah Islam yang tidak ramah dan cenderung menampilkan konservatisme.
Dalam pandangan para tokoh JIL, publik saat itu diwarnai dengan pemahaman masalah sosial keagamaan yang radikal dan anti-pluralisme. Kondisi inilah yang kemudian mendorong beberapa aktivis muda untuk melakukan berbagai diskusi di Jalan Utan Kayu 68 H Jakarta Timur.
Kemudian dengan merujuk kepada tempat itulah maka beberapa tokoh muda Islam mendirikan Komunitas Islam Utan Kayu yang merupakan cikal bakal berdirinya JIL. Beberapa nama yang terlibat untuk membentuk Komunitas Utan Kayu itu dan kemudian mendirikan JIL antara lain Ulil Abshar-Abdalla, Nong Darol Mahmada, Burhanuddin, Ihsan Ali Fauzi, Hamid Basyaib, Taufiq Adnan Amal, Saiful Mujani, dan Luthfi Assaukanie.
Beberapa tema yang menjadi bahan diskusi di antara aktivis tersebut antara lain: maraknya kekerasan atas nama agama, gencarnya tuntutan penerapan syariat Islam, serta tidak adanya gerakan pembaruan pemikiran Islam yang sebelumnya dirintis oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid.
Nama Islam liberal, menurut para pendiri JIL, adalah menggambarkan komunitas Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial politik yang ada. Menurut para aktivis JIL, Islam liberal adalah suatu bentuk penafsiran tertentu atas Islam dengan landasan sebagai berikut: 1) Membuka pintu ijtihad pada semua dimensi; 2) Mengutamakan semangat religio etik, bukan makna literal teks; 3) Mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural; 4) Memihak pada yang minoritas dan tertindas; 5) Meyakini kebebasan beragama; 6) Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrowi, otoritas keagamaan dan politik. Islam liberal yakin bahwa kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan.
Secara umum, kegiatan-kegiatan JIL ditujukan untuk turut memberikan kontribusi dalam meredakan maraknya fundamentalisme keagamaan di Indonesia sekaligus membuka pemahaman publik terhadap pemahaman keagamaan yang pluralis dan demokratis. Secara khusus, kegiatan-kegiatan JIL ditujukan untuk: 1) Menciptakan intellectual discourses tentang isu-isu keagamaan yang pluralis dan demokratis serta berperspektif gender; 2) Membentuk intellectual community yang bersifat organik dan responsif serta berkemauan keras untuk memperjuangkan nilai-nilai keagamaan yang suportif terhadap pemantapan konsolidasi demokrasi di Indonesia; 3) Menggulirkan intellectual networking yang secara aktif melibatkan jaringan kampus, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan lain-lain untuk menolak fasisme atas nama agama.
Sebagaimana sebuah pemikiran baru, selalu menimbulkan pro dan kontra. Demikian juga dengan JIL. Sikap pro-kontra terhadap JIL dapat dipetakan menjadi dua yaitu dalam bentuk fisik dan intelektual. Dalam bentuk intelektual dapat dilihat dari terbitnya berbagai buku baik yang menghujat maupun menanggapi secara positif. Beberapa penulis yang menentang JIL yang dibukukan antara lain Adian Husaini, Adnin Armas,Yudhi R. Haryono, Hartono Ahmad Jaiz, dan Fauzan al-Anshari.
Sementara itu ada juga yang mencoba berpikir obyektif ilmiah, menjadikan JIL sebagai fokus bahasan untuk menyusun skripsi, tesis, maupun disertasi. Sementara itu, sebagian kelompok masyarakat Islam menganggap bahwa pemikiran JIL dianggap dapat merusak aqidah umat Islam. Oleh karena itu mereka menentangnya dalam bentuk kekerasan fisik. Hal itu antara lain dalam bentuk demontrasi oleh Front Pembela Islam (FPI).
Beberapa kali milis yang dikelola JIL juga mendapat serangan spam dan dibajak oleh hacker-hacker. Sementara itu Forum Ulama Umat Islam (FUUI) di Bandung mengeluarkan fatwa mati kepada Ulil sebagai ketua JIL. Institusi JIL juga semakin diributkan setelah keluar fatwa MUI yang mengharamkan faham liberalisme, sekularisme dan pluralisme.
Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM)
Menurut Ahmad Najib Burhani dalam Imam Tholkhah dan Neng Dara Afiah (2005: 352-399), tidak terlalu jelas kapan terbentuknya Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (selanjutnya ditulis JIMM). Pada pertengahan tahun 2003 banyak berita dan opini dalam media massa nasional memuat tulisan tentang JIMM atau artikel-artikel yang ditulis oleh intelektual tokoh JIMM. Tiba-tiba pula sejumlah anak muda Muhammadiyah menggabungkan diri dan terlibat dalam aktivitas intelektual bersama dalam berbagai workshop, seminar, diskusi, penelitian ilmiah dan sejenisnya.
Walaupun tidak ditetapkan secara pasti kapan JIMM dibentuk, tetapi ada beberapa peristiwa, internal dan eksternal, yang mengiringi kebangkitan inteletual muda Muhammadiyah. Dari sisi internal, paling tidak terdapat tiga faktor. Pertama, geliat pemikiran Muhammadiyah pasca Muktamar ke-43 yang dimotori antara lain oleh M. Amien Rais, Ahmad Syafii Ma‘arif dan M. Amin Abdullah. Kedua, masuknya kembali pemikirpemikir Muhammadiyah seperti Moeslim Abdurrahman. Ketiga, pendirian Maarif Institute for Culture and Humanity yang awalnya dirancang untuk memperingati ulang tahun Ahmad Syafii Ma‘arif ke 70. Sedangkan dari sisi eksternal, JIMM lahir sebagai respon agresifitas generasi muda NU (Nahdlatul Ulama) yang mewarnai pemikiran dan gerakan Islam kontemporer, baik yang bersifat individual maupun yang tergabung dalam lembaga seperti LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial), JIL (Jaringan Islam Liberal), Lakpesdam NU, P3M, dan Desantara. Agresifitas tersebut telah memicu kecemburuan di kalangan muda Muhammadiyah yang kalau dilihat dari label yang disandang Muhammadiyah, sebagai gerakan Islam pembaru dan Islam modernis, seharusnya memiliki pemikiran jauh ke depan dibanding dengan aktivis muda NU.
Bagi para aktivis JIMM sendiri, ada tiga alasan kenapa JIMM didirikan. Pertama, JIMM hadir katanya untuk mengawal tradisi tajdid (pembaruan) yang belakangan cenderung meredup. Kedua, JIMM lahir untuk mengisi kesenjangan intelektual antar-generasi di Muhammadiyah, sehingga JIMM diharapkan dapat menjadi arena kaderisasi intelektual muda Muhammadiyah. Ketiga, JIMM lahir sebagai respon terhadap tantangan dan tuduhan dari luar Muhammadiyah.
Kelahiran JIMM menimbulkan reaksi pro dan kontra, baik dari kalangan generasi senior Muhammadiyah maupun dari luar warga Muhammadiyah. Beberapa sesepuh Muhammadiyah mencurigai keberadaan JIMM sebagai kepanjangan tangan dari gerakan liberalism di Indonesia, agen Barat untuk melakukan hegemoni terhadap umat Islam, bahkan dianggap telah melanggar aturan organisasi Muhammadiyah.
Sejak awal kelahirannya, JIMM memancangkan tiga pilar sebagai strategi gerakannya yaitu hermeneutika, teori sosial dan new social movement. Penggunaan hermeneutika dimaksudkan untuk mendobrak pendekatan dan pemahaman struktural yang dominan di kalangan Muhammadiyah. Dengan hermeneutika maka akan terjadi reproduction of new meaning. Teori-teori sosial kritis,-—seperti kerangka teoritik Antonio Gramsci untuk menolak hegemoni, atau teori Paulo Freire untuk pembebasan kaum tertindas—-digunakan sebagai peralatan intelektual Islam. Dengan memanfaatkan teori sosial kritis maka diharapkan warga Muhammadiyah tidak hanya berfungsi sebagai mediator tetapi sebagai artikulator bagi transformasi sosial. Sedangkan dengan konsep the new social movement menjadikan teologi bukan hanya semata-mata sebagai disiplin ilmu tetapi menjadi sebuah gerakan. Seluruh elemen masyarakat yang selama ini terpinggirkan, digerakkan oleh teologi untuk bersatu melakukan perubahan bersama.
Demikian beberapa deskripsi singkat tentang gerakan Islam liberal di Indonesia. Masih ada beberapa organisasi lain yang tidak disebutkan di sini seperti FORMACI, LKiS Yogyakarta, Letsform (Lembaga Transformasi Muhammadiyah) Jawa Barat, dan Pesantren Mahasiswa An-Nur Wonocolo Surabaya, tetapi pengaruh mereka hampir dapat diabaikan.
Catatan Penutup
Rincian hasil pemikiran JIL tentang hukum Islam dan masalah-masalah lain sebenarnya belum tertuang secara lengkap, melainkan masih merupakan letupan-letupan pemikiran keagamaan yang sifatnya sporadis.
Demikian pula kerangka metodologis berpikirnya juga belum tertuangkan secara utuh dan jelas. Karena itu, untuk menganalisisnya secara komprehensif tidaklah mungkin kecuali sekedar mendasarkan diri pada percikan-percikan pemikiran yang sepotong-sepotong itu.
Menurut Greg Barton, beberapa karakteristik pemikiran Islam liberal di Indonesia antara lain: 1) senantiasa mengusung semangat ijtihad; 2) mengusung rasionalisme; 3) menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi; 4) menjunjung tinggi peran ilmu pengetahuan; 5) memandang bahwa keinginan mendirikan "negara Islam" adalah pengalihan perhatian yang merugikan; 6) menerima dan mendukung pluralisme masyarakat; 7) memegangi prinsip-prinsip humanitarianisme, bahkan memandangnya sebagai essensi dan jantung Islam; 8). memperjuangkan kesetaraan gender.
Jika pengamatan Greg Barton itu benar, maka pemikiran Islam liberal nampaknya positif untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Tetapi nampaknya Greg Barton terlalu bersimpati terhadap pemikiran Islam liberal, atau ia sebenarnya tidak berpikir mengenai Islam liberal sebagai suatu kelompok atau jaringan, melainkan hanya sebagai suatu kecenderungan pemikiran.
Ia juga tidak secara eksplisit membedakan antara liberalisasi pemikiran Islam, dan pembaharuan pemikiran Islam, yang biasa disandang oleh kaum modernis. Tentu saja, liberalisasi berbeda dengan pembaharuan. Dalam pembaharuan, yang ada ialah reformulasi pemikiran Islam terhadap teks-teks suci (nash) yang ada. Sedangkan dalam liberalisasi terkandung makna keberanjakan (departure) dari teks suci (nash). Dengan kata lain, dalam liberalisme ada unsur meninggalkan nash. Dan inilah yang ditentang oleh MUI.
Menurut Hartono Ahmad Jaiz, di antara pendapat-pendapat kaum pendukung Islam liberal adalah sebagai berikut (Hartono Ahmad Jaiz, 2005: 109-110): 1) Al-Quran adalah teks dan harus dikaji dengan hermeneutika; 2) Kitab-kitab tafsir klasik itu tidak diperlukan lagi; 3) Poligami harus dilarang; 4) Mahar dalam perkawinan boleh dibayar oleh suami atau isteri; 5) Masa iddah juga harus dikenakan kepada laki-laki, baik cerai hidup ataupun cerai mati; 6) Pernikahan untuk jangka waktu tertentu boleh hukumnya; 7) Perkawinan dengan orang yang berbeda agama dibolehkan kepada laki-laki atau perempuan muslim; 8) Bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan sama 1:1; 9) Anak di luar nikah yang diketahui secara pasti ayah biologisnya tetap mendapatkan hak warisan dari ayahnya.
Jika pendapat-pendapat di atas dicermati maka akan Nampak sejumlah kesimpangsiuran cara berpikir JIL, dan kecenderungan melonggar-longgarkan aturan agama seperti hendak melihatnya sama seperti aturan buatan manusia. Untuk lebih jelasnya pendapat-pendapat itu dapat kita lihat satu-persatu sebagai berikut.
1. Al-Quran adalah teks dan harus dikaji dengan hermeneutika
Mengkaji Al-Quran sebagai teks dengan konteks bukanlah sesuatu cara yang terlalu baru. Apalagi istilah hermeneutika pun mempunyai banyak makna. Ada makna pada tataran filosofis, dan ada makna pada tataran sosiologis dan historis. Sesungguhnya, ulama tafsir klasik pun telah menggunakan kajian Asbabun Nuzul yang memberi konteks dari turunnya sesuatu ayat. Apa yang dikhawatirkan orang ialah bahwa penggunaan kajian hermeneutika terhadap Al-Quran, akan berarti penerapan kajian biblikal untuk al-Qur’an, dan memalingkan arti teks Al-Quran dengan dalih hermeneutika. Ada kekeliruan asumsi di sini, antara perbedaan status teks
Al-Quran yang selamanya orisinal sebagai wahyu Tuhan, dan teks biblical yang ditulis oleh orang-orang yang hidup beberapa lama setelah Nabi Isa.
2. Kitab-kitab tafsir klasik itu tidak diperlukan lagi
Jika ini adalah pendapat JIL, maka ini adalah pertanda kerancuan berpikir yang jelas, karena komunikasi dengan pemikiran para mufasir klasik itu sangat diperlukan justeru antara lain untuk memahami konteksnya, dan memahami konteks masyarakat mereka. Dan pemahaman konteks itu adalah anjuran dari hermeneutika. Jadi, kalau kitab-kitab klasik tidak diperlukan lagi, sebenarnya bertentangan dengan anjuran penggunaan hermeneutika itu sendiri.
3. Poligami harus dilarang
Pelarangan atas poligami sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Di Turki dan Tunisia, hal itu sudah berjalan lama. Tetapi pelarangan itu pun tidak berarti mengubah larangan Islam yang sudah diatur dalam Al Quran, bahwa poligami itu memang diperbolehkan dengan syarat-syarat
tertentu. Pelarangan poligami di Turki dan Tunisia itu hanyalah bersifat menon-aktifkan sesuatu aturan syariat pada suatu masa di suatu tempat tertentu. Hal itu juga pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika memberhentikan pemberlakukan hukum potong tangan atas pencuri dalam konteks tertentu pada waktu tertentu dan di tempat tertentu. Umar bin Khattab sama sekali tidak mengklaim bahwa aturan syariat tentang hukum potong tangan dalam Al-Quran itu telah ditiadakan. Masalahnya ialah, boleh jadi pada suatu ketika nanti di suatu masyarakat tertentu, karena peperangan misalnya, akan terjadi ketidakseimbangan yang besar antara penduduk laki-laki dan perempuan, dimana jumlah penduduk perempuan jauh melebihi jumlah penduduk laki-laki. Dalam hal demikian, maka poligami pada saat itu justeru mungkin harus dianjurkan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, teks Al-Quran tentang kebolehan poligami tidak perlu dihapuskan. Saran penghapusan seperti itu sesungguhnya menunjukkan kerancuan berpikir antara aturan sebagai hukum dan pelaksanaan aturan hukum sebagai kemaslahatan di lapangan.
4. Mahar dalam perkawinan boleh dibayar oleh suami atau isteri
Dalam bahasa Inggris, kata dowry memang bisa berarti pemberian dari pihak calon suami kepada calon isteri atau sebaliknya. Pemberian seperti itu tentu saja tidak bermasalah, baik dilakukan sebelum maupun sesudah perkawinan. Bahkan tukar menukar pemberian pun tentu baik-baik saja. Tetapi mahar dalam konteks akad nikah adalah pemberian calon suami kepada calon isteri sebagai simbol bahwa mulai saat itu tanggung jawab nafkah isteri berada pada pihak suami. Makna simbolik ini tentu tidak bisa dibalik menjadi pemberian isteri kepada suami.
5. Masa iddah juga harus dikenakan kepada laki-laki, baik cerai hidup ataupun cerai mati.
Di sini terjadi kerancuan antara berpikir hukum dan berpikir psikologis. Masa iddahbagi perempuan memang mengandung aspek psikologis karena tentu tidak etislah seseorang perempuan yang baru sehari diceraikan suaminya atau kematian suaminya kemudian menikah lagi.
Tetapi lebih penting dari itu, wanita harus menunggu pembuktian ada tidaknya kehamilan di dalam dirinya. Meskipun alat-alat kedokteran baru mungkin mampu mendeteksi ketiadaan kehamilan pada hari pertama setelah perceraian atau kematian suami, tetapi kesempurnaan pemahaman itu baru akan terjadi setelah tiga kali putaran menstruasi atau 4 bulan dan 10 hari setelah kematian suami. Laki-laki pun secara psikologis memang perlu waktu menunggu setelah perceraian atau kematian istrinya sebelum melakukan perkawinan baru, tetapi waktu tunggu itu semata-mata masalah psikologis dan bukan masalah kejelasan keturunan kelak, seperti terjadi pada perempuan. Jadi memang ada perbedaan antara berpikir secara hukum dan berpikir secara psikologis.
6. Pernikahan untuk jangka waktu tertentu boleh hukumnya
Pendapat ini terkesan terpengaruh oleh pendapat kaum syiah yang selama ini memang memperbolehkan nikah mut’ah atau kawin untuk jangka waktu tertentu. Nikah mut’ah memang pernah dibolehkan pada zaman Nabi, tetapi kemudian dilarang kembali. Konteksnya pada waktu itu ialah bahwa pasukan yang berperang di negeri jauh tidak memungkinkan berkomunikasi dengan isterinya, karena teknologi komunikasi belum memungkinkan. Sekarang ketika teknologi komunikasi begitu mudah, ada korespondensi, SMS, email, telepon suara, telepon bergambar, video, dan sebagainya, maka komunikasi dapat dilakukan ke manapun suami pergi. Karena itu, usul untuk membuka kembali pintu nikah mut’ah sebenarnya justeru tidak berpikir kontekstual. Usul seperti itu lebih dikhawatirkan sebagai upaya melonggar-longgarkan aturan agama. Apalagi lembaga nikah mut’ah itu memang telah jelas-jelas dilarang.
7. Perkawinan dengan orang yang berbeda agama dibolehkan kepada laki-laki atau perempuan muslim
Sama halnya dengan usul pelarangan poligami, untuk masalah ini pun perlu pembedaan antara hukum pada tataran syariat dan pada tataran pelaksanaan. Kita tidak perlu dan tidak boleh menghapus aturan syariat, tetapi kita boleh menonaktifkan sementara suatu aturan hukum di tempat tertentu karena illattertentu, yang kemudian harus diubah kembali ketika illat itu tidak ada. Melonggar-longgarkan aturan agama, atau memperketat-ketatkan aturan agama adalah sama tidak bolehnya. Karena itu fatwa MUI yang mengharamkan laki-laki muslim kawin dengan non muslim yang ahli kitab adalah juga berlebihan. Fatwa seperti itu hanya dapat diterima apabila dimaksudkan hanya untuk menjaga kemaslahatan dalam konteks tertentu untuk waktu tertentu dan di tempat tertentu.
8. Bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan sama 1:1
Di Turki, Tunisia, dan Somalia, pernah diberlakukan undang-undang yang mengatur warisan untuk anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Di Indonesia pun, melalui Kompilasi Hukum Islam, hal itu dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara para ahli waris yang ada, setelah mereka mengetahui bagiannya masing-masing. Tetapi sekali lagi teks nash tidak perlu diubah, karena pada suatu ketika mungkin akan terjadi suatu konteks yang justeru menginginkan apa yang diatur oleh teks nash sekarang ini.
9. Anak di luar nikah yang diketahui secara pasti ayah biologisnya tetap mendapatkan hak warisan dari ayahnya
Lagi-lagi di sini terjadi kerancuan antara berpikir hukum dan berpikir non-hukum. Nikah adalah suatu lembaga yang secara hukum memberikan legalitas. Pada sisi lain, hak warisan adalah salah satu bentuk hak hukum. Karena itu, berbicara hak warisan harus didasarkan kepada hak-hak hukum, dan hak hukum hanya ada pada legalitas.
Demikianlah beberapa catatan di seputar berbagai pemikiran kaum Islam liberal di Indonesia. Agar supaya perdebatan pemikiran itu lebih sehat, sebaiknya mereka yang mengumandangkan pembaruan atau liberalisasi atau apapun namanya, merumuskan secara cermat dan menyeluruh kerangka berpikir metodologis mereka, sehingga tidak sekedar menimbulkan kontroversi yang sesungguhnya sia-sia dan tidak berujung.
Wallahu a’lam bish shawab.
Catatan Akhir
1 Makalah disajikan dalam Seminar Internasional Tajdid Pemikiran Islam, bertema "Ahlus Sunnah Wal Jamaah di Era Liberalisasi Pemikiran Islam," diselenggarakan atas kerjasama Yayasan Dakwah Islam Malaysia-Indonesia (YADMI), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, pada tanggal 10 September 2009. Makalah ini pernah disampaikan penulis sebagai anggota delegasi Menteri Agama RI pada Musyawarah SOM ke-31 dan MABIMS ke-12 di Kuala Lumpur Malaysia, tanggal 28-30 November 2006. Dalam bentuknya yang sekarang, makalah ini diberi perubahan dan tambahan pada bagian catatan akhir.
Daftar Pustaka
Abdurrahman Wahid, "NU dan Islam di Indonesia Dewasa ini", Prisma, No 4 April 1984.
Abdurrahman Wahid "Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa", Prisma, nomor ekstra, 1984.
Adian Husaini, Pluralisme Agama: Haram, Fatwa MUI yang Tegas & Tidak Kontroversial, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Ahmad Najib Burhani, "Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM): Pemberontakan Melawan Puritanisme dan Skripturalisme Persyarikatan" dalam Imam Tholkhah dan Neng Dara Afiah (ed.), Gerakan Keislaman Pasca Orde Baru: Upaya Merambah Dimensi Baru Islam, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, t.th.
Fachri Aly & Bachtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru, Bandung, Mizan, 1986.
Hartono Ahmad Jaiz, Ada Pemurtadan di IAIN, Jakarta, Pustaka Al Kautsar, 2006.
Keputusan Fatwa MUI No. 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.
Nong Darol Mahmada dan Burhanuddin, "Jaringan Islam Liberal (JIL): Pewaris Pemikiran Pembaruan Islam di Indonesia" dalam Imam Tholkhah dan Neng Dara Afiah (ed.), Gerakan Keislaman Pasca Orde Baru: Upaya Merambah Dimensi Baru Islam, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, t.th.
Nurcholish Madjid, "Suatu Tatapan Islam terhadap Masa Depan Politik Indonesia", Prisma, nomor ekstra,1984.