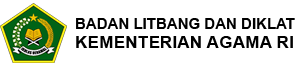Syahdunya Azan dan Ritmisnya Lonceng Gereja;

(Cerita Toleransi yang Mengesankan dari Tana Lepongan Bulan)
Syamsurijal
Toraja (Balitbang)--Gelap baru saja jatuh ke bumi, saat rombongan kami mendekat ke gerbang perbatasan Tana Lepongan Bulan, kini disebut Tana Toraja, salah satu kabupaten di ujung utara Sulawesi selatan. Gapura berwujudtongkonan (rumah adat yang berwujud rumah panggung; simbol kekerabatan) samar-samar menjulang gagah di keremangan senja yang terlihat semakin kelam. Sinar lampu kendaraan menolong kami untuk tetap bisa melihat jelas keberadaan pintu gerbang tersebut.
Begitu melewati gerbang, suasana gelap dan hujan berinai-rinai yang tiba-tiba runtuh dari langit membuat kami kesulitan untuk melihat suasana sekeliling. Tetapi sekali dua kali, kami masih bisa menikmati rumah ibadah yang tegak menjulang sepanjang kami melewati perbatasan Toraja. Gereja dan juga masjid, terlihat berdiri di sisi jalan. Tak jarang letak antara masjid dan gereja terasa tidak berjauhan, sebab baru beberapa saat kami melihat gereja, tak berapa lama kami juga sudah menyaksikan masjid yang berdiri anggun.
Kedatangan kami ke Lepongan Bulan dalam rangka pembuatan film pendek bertema toleransi beragama. Judulnya Tondok Solata (Kampung Persahabatan). Film ini adalah salah satu proyek Litbang Agama Makassar untuk menyambungkan moderatisme agama ke kalangan milenial.
Kaum milenial ini memiliki dunia sendiri yang sedikit banyaknya ditentukan oleh internet dan media sosial. Karena itulah kampanye soal moderatisme agama harus bisa dinikmati melalui media sosial pula, seperti youtube, whatsapp, instagram ataupun facebook. Salah satu bentuk penyajiannya adalah film-film pendek atau film dokumenter. Jika para pengusung moderatisme agama tidak melakukan itu, maka percayalah kalangan milenial akan diterkam oleh ekstremisme agama di media sosial.
Sudah barang tentu memilih Toraja sebagai lokasi pembuatan film pendek tentang toleransi bukan tanpa sebab. Tidak hanya kabar lisan, tapi juga beragam tulisan telah melukiskan indahnya kerukunan beragama di daerah ini. Saya sendiri telah berkali-kali berkunjung ke daerah ini dan setiap kali kunjungan itu, saya dapat merasakan kehangatan masyarakat Lepongan Bulan. Sebagai seorang muslim, saya diterima di kampus Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STKN-tempat yang paling sering saya kunjungi), layaknya kerabat dan sahabat yang sangat dekat.
Dalam kunjungan kali ini pun saya merasakan pengalaman toleransi yang mengesankan di daerah ini. Di mulai saat subuh hari mulai merayap. Dari tempat saya menginap di Rantepao, azan terdengar berkumandang dari Mesjid Agung. Panggilan untuk melaksanakan salat subuh bagi kaum muslim berkumandang menembus dinding rumah, mengelus kalbu agar segera bangkit dari peraduan. Tak berselang lama, lonceng gereja pun terdengar bertalu-talu. Suara ritmisnya merayap-rayap di udara, mengingatkan kaum Nasrani, baik Kristen maupun yang Katolik untuk bangun beribadah pagi. Di Katolik diistilahkan dengan tuguran (ibadat subuh) atau laudes(ibadat pagi).
Panggilan syahdu dari azan subuh, diikuti tak lama kemudian oleh irama lonceng yang ritmis. Perpaduan dua irama spiritualitas yang memukau. Kata orang yang tinggal di sekitar tempat itu, peristiwa itu telah berlangsung lama. Tak pernah menimbulkan masalah, bahkan terasa sebagai perpaduan rohani yang menawan.
Dan benarlah..., cerita azan dan lonceng gereja yang terdengar beriringan itu adalah penanda awal, bahwa warga Toraja hidupnya selama ini memang selalu seiras-seirama, meski mereka tidak harus satu agama.
Imam Mesjid Agung Rantepao, Ustadz Mujahidin, yang telah berdiam lebih kurang tiga puluh tahun di Toraja ini merasakan betapa hangatnya kekerabatan di tempat ini. Bukan hanya karena orang Nasrani yang berada di sekitarnya, selalu ramah padanya, tapi juga orang Nasrani itu selalu menjaga umat Islam saat menjalankan ibadah.
“Saat lebaran Idul Fitri, saudara-saudara dari Nasrani ikut menjaga ibadah kami, sebaliknya jika perayaan Natal kami pun terlibat menjaga suasana aman," kata Ustadz Mujahidin dengan paras yang sumringah.
Tentu pandangan Ustadz Mujahidin dalam menggambarkan keragaman di Tana Lepongan Bulan ini berkaitan dengan apa yang ia rasakan; bagaimana keberadaannya di tengah komunitas yang mayoritas beragama berbeda dengannya, bagaimana pula ia diperlakukan, dan seterusnya.
Singkatnya, Ustadz Mujahidin melihat keragaman dan kehidupan di tempat ia berada. Baru dari situlah ia dapat melihat konteks keberagaman itu apa adanya. Sesuai kutipan Kenan Malik: "We don’t see things (diversity) as they are, we see things as we are".
Hari berikutnya dalam kunjungan ke Tana Lepongan Bulan, kami mengunjungi salah satu tongkonan yang bernamaTongkonan Ne’Leppe To’ Karau Nek Fany. Di tempat ini kami menyaksikan orang Muslim dan Kristen berdiam di sekitar tongkonan tersebut dengan damai. Dua tokoh adat yaitu Yunus Tajuddin beragama Islam dan Cornelius Pasulu dari Kristen, menyambut kami dengan ramah. Tokoh adat muslim datang dengan kopiah hitam, berkaus hitam dan bersarung, sementara yang Kristen mengenakan sarung, tapi tak berkopiah.
Ketika waktu salat tiba, Cornelius memberi isyarat kepada Yunus Tajuddin untuk menyiapkan tempat dan peralatan salat untuk kami. Yunus bergegas menyiapkan sajadah, sementara Cornelius meminta kepada beberapa anak muda untuk membersihkan lantai di bawah Tongkonan untuk salat.
Ibu Naomi, seorang Nasrani dosen di STKN yang ikut dalam rombongan, menawarkan bila ingin salat di atas tongkonan tidak jadi soal. Tawaran yang terlihat bersungguh-sungguh, bukan sekedar basa-basi. Peristiwa itu cukup mengesankan. Saya pun memang akhirnya salat di sana, tidak di atas tongkonan tapi di bawahnya. Tidak salah jika akhirnya peristiwa itu menjadi inspirasi sutradara film Tondok Solata, Baso Marannu, untuk menjadi bagian dari fragmen dalam film.
Dari situ pulalah kami mendapat penjelasan bahwa di Toraja atau Tana Lepongan Bulan ini, makanan halal sangat diperhatikan oleh masyarakat. Uniknya yang sangat memperhatikan soal ini adalah orang-orang Nasrani. Karena itu di setiap acara, baik hanya pesta keluarga maupun acara ritual adat, pembagian hidangan makanan bagi muslim dan yang bukan muslim, selalu dilakukan. Tidak hanya makanannya, bahkan ruangannya, tempat makanannya dan proses mengolah makanannya juga dibedakan.
“Sering kali acara-acara tertentu hanya menghidangkan makanan yang bisa disantap kaum muslim, tidak lagi menyajikan makanan lainnya, demi menghormati kami yang muslim ini," ungkap Yunus Tajuddin, Tokoh Adat Muslim yang menemui kami di sekitar Tongkonan Ne’ Leppe To’Karau.
“Karena itu jangan ragu menyantap hidangan jika hadir di acara-acara atau pesta di sini Pak, kami sudah memiliki kearifan lokal untuk mengaturnya sedemikian rupa," sambung Ibu Naomi.
Mendengar itu, Faisal seorang sejawat peneliti Litbang Agama Makassar yang sebelumnya sudah tinggal cukup lama di Tana Toraja, mengangguk membenarkan. Faisal sendiri sudah merasakan bagaimana menghadiri acara-acara dan pesta adat dan bagaimana ia disuguhkan makanan.
Penghormatan dan hidup damai antara pemeluk agama yang berbeda ternyata bersumber dari adanya tradisi tongkonan. Sepintas atau jika dilihat secara fisik, tongkonan hanyalah rumah adat masyarakat Toraja dengan bentuknya yang unik. Namun sebenarnya tongkonan adalah simbol ikatan kekerabatan.
Tongkonan menjadikan kekerabatan antara masyarakat Toraja, terjalin dengan kuat, meskipun berbeda agama. Melalui tongkonan, begitu penjelasan pendeta Daud Sangka, tidak ada agama yang dipandang lebih rendah atau lebih tinggi. Semua sama dan setara meski yang satu lebih banyak pemeluknya dibanding yang lain. Ibaratnya dalam pepatah: “Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Berkuah sama menghirup, bersambal sama mencolek”
Melalui tongkonan, menyambut yang lain yang berbeda, dipraktikkan secara riil. Jika ada acara keluarga atau upacara adat yang berlangsung di tongkonan, yang Nasrani menyambut yang Muslim, begitu pun sebaliknya. Perayaan keragaman begitu gamblang terlihat di dalam Tongkonan itu. Di dalam dan melalui tongkonan, Qabul Al-akhar (menyambut sang lian) begitu istilah Milad Hanna, nyata dilaksanakan di masyarakat Tana Lepongan Bulan ini.
Lima hari lamanya berada di Tana Lepongan Bulan, banyak kisah yang melukiskan kerukunan masyarakat di daerah ini. Cerita-cerita yang berkesan, namun tidak semua bisa saya tumpahkan dalam tulisan ini. Biarlah tetap jadi kenangan, suatu saat cerita itu bisa kembali diukir dalam goresan pena yang berbeda. []
Sumber foto: google
syamsurijal/diad