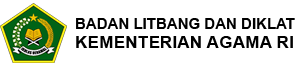Menelisik Nilai-nilai Leluhur dalam Manuskrip Kuno: “Kontradiksi Perang, Agama, dan Budaya Damai dalam Manuskrip Kuno”

Jakarta (19 Februari 2020). Diskusi tentang manuskrip kuno selalu menarik. Apalagi tema yang diusung cukup aktual dengan konteks kekinian yaitu “Kontradiksi Antara Perang, Agama, dan Budaya Damai”. Bertempat di Lantai 2 Gedung Kementerian Agama, pada hari Kamis, 19 Februari 2020, Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (Puslitbang LKKMO) menyelenggarakan diskusi bersama Profesor Edwin Wieringa, Profesor Fhilology dan Islamic Studies dari Koln University, Jerman, dengan tema “Persoalan Perang dalam Naskah Islam Indonesia: Sekitar Nilai-nilai Leluhur”. Diskusi tersebut mampu memberi pencerahan bahwa memaknai sebuah teks tidak mesti secara superficial, melainkan secara lebih mendalam dan melibatkan juga konteks yang melatarinya.
Prof. Edwin Wieringa yang sedang mengikuti fellowship di Perpustakaan Nasional Singapura meluangkan waktu untuk menjadi narasumber diskusi bersama para peneliti Badan Litbang dan Diklat khususnya Puslitbang LKKMO. Materi yang dipaparkan sangat menarik, karena mencoba membuka pikiran audience untuk melihat sebuah subjek kajian (teks) dari sisi sastra. Sesuai dengan keahliannya dalam bidang sastra, narasumber mengungkapkan terlebih dahulu perbedaan makna dari sastra dan susatra. Sastra lebih kepada pedoman dan pesan-pesan moral yang serius, sementara susastra lebih kepada keindahan (belletters). Karena itu, sebuah teks tidak bisa dipahami dengan apa yang tertulis di dalamnya, melainkan perlu dilihat pesan di dalamnya yang dilatarbelakangi oleh lingkungan, masa, dan masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya, pembaca harus mampu menangkap “makna luaran” (external meaning) dengan “makna spiritual” (spiritual meaning) atau makna sejati dari teks, agar bisa memahami makna teks secara keseluruhan.
Narasumber juga mengulas tentang “perang dan kekerasan” dalam teks. Terdapat perbedaan pandangan bagi orang yang beragama dan tidak beragama. Orang yang tidak beragama akan menganggap agamalah yang memicu kekerasan. Sementara, orang yang beragama menolak kekerasan, karena agama membawa pesan cinta kedamaian. Kekerasan (radikalisme/ekstremisme) sudah barang tentu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kontradiksi dua pandangan tesebut dapat disatukan dengan pernyataan bahwa tidak ada kekerasan dalam agama, tentunya dengan memahami secara benar teks yang dibaca serta tidak mengklaim secara sembarangan terhadap sesuatu kelompok dan agama.
“Penyajian perang dalam teks sastra bisa jadi memiliki banyak makna. Penggambaran adegan perang dalam teks adalah simbol, bukan budaya untuk merayakan kekerasan. Di dalamnya memuat arti pengorbanan dan menunjukkan kekuatan suatu bangsa. Karena itu, pemahaman teks sastra tidak bisa dipahami secara harfiah,”demikian tegas Weiringa.
Dalam diskusi, narasumber mencontohkan kisah tentang perang dan kepahlawanan, yaitu Hikayat Muhammad Ali Hanafiyah. Hikayat ini secara harfiah menggambarkan peperangan dan kekerasan yang tak terbatas, di mana di dalamnya memuat unsur kekejaman, penipuan, pembunuhan, dan mutilasi. Teks ini akan sangat membosankan apabila dibaca generasi sekarang, ditambah lagi pembaca tidak mengetahui latar dan konteks pada saat hikayat tersebut ditulis. Tentu kisah ini sangat digemari oleh pembaca yang hidup pada masa hikayat ini ditulis. Apakah karena unsur susastranya yang mengedepankan hiburan ? Atau menarik karena kisah spirit kepahlawanan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran? Alasan tentang betapa menariknya hikayat tersebut di masanya tentu memerlukan kajian lebih mendalam.
Contoh lain yang dikutip oleh narasumber adalah naskah pra-Islam “Kakawin” yang di dalamnya juga mengisahkan pertumpahan darah dan kekerasan selama peperangan. Namun, apabila dibaca lebih jauh dengan mendalami konteks saat itu, maka akan terlihat bahwa kisah peperangan tersebut memuat nilai-nilai luhur terkait dengan pengorbanan dalam memperjuangkan kehidupan, di samping memperhatikan taktik dan strategi perang. Selain itu, narasumber juga menyebut tentang Hikayat Hang Tuah yang sangat populer di Malaysia. Hikayat ini ditulis pada saat seorang raja (Hang Tuah) yang mempunyai kekuasaan mutlak dan merupakan bayangan Allah di bumi. Oleh karenanya, ia tidak boleh dikritik dan harus diikuti kemauannya oleh Si Durhaka Hang Jebat. Kisah kepahlawanan Hang Tuah ini, meskipun di dalamnya sarat dengan muatan kekerasan, bahkan ditetapkan sebagai manuskrip warisan leluhur paling berharga di Malaysia karena dipandang menggambarkan tamadun/budaya dari bangsa Melayu.
Selama diskusi, peserta terlihat sangat antusias menggali ilmu dari Prof. Edwin terkait tema yang dibahas. Hampir semua peserta mengajukan pertanyaan, komentar, sharing ide, dan juga apresiasi terhadap presentasi narasumber. Dari hasil diskusi ini, ada satu statemen penting yang patut diperhatikan dan bisa diadaptasi dalam kehidupan, yaitu membaca sebuah teks harus cerdas, agar kita tidak memaknai teks secara sempit, tidak mengambil kesimpulan seperti apa yang tertulis saja, namun cerdas memahami konteks yang dikaitkan dengan berbagai sisi pada masanya dan pada masa akan datang. Al-hasil, teks sastra akan menarik dibaca dan tetap bisa hidup sampai kapan pun. Revitalisasi naskah kuno yang mengandung sastra dan susastra yang tinggi dapat diwujudkan. (Fakhriati/bas/ar)