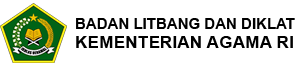MEMAJUKAN PENDIDIKAN INDONESIA

Muhamad Murtadlo
Refleksi disampaikan dalam acara Syukuran 73 tahun
Kiprah Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI), Bekasi 12 Maret 2023
Awal Maret 2023, saya untuk kesekian kali berkesempatan berkunjung ke Singapura. Kali ini kunjungan setelah Pandemi covid-19 mulai berlalu. Kebetulan saat itu dapat undangan menghadiri Rapat Koordinasi Kementerian Agama untuk membicarakan Kerjasama dengan Pusat Riset Pendidikan BRIN di Batam Kepulauan Riau, dan di hari terakhir bersama teman-teman panitia kita mampir sehari ke Singapura.
Beberapa kali saya mengunjungi negara itu, saya juga berkesempatan Shortcourse 3 bulan di National University of Singapore (NUS). Tidak terlalu istimewa Singapura saat ini dibandingkan waktu pertama kali saya berkunjung ke sana. Saat itu (2009) saat menyeberang dari Batam pertama kali dan tiba di Harbort Front (Singapura), mata saya terbelalak, terheran-heran ada peradaban dekat Indonesia yang sedemikian maju. Rasanya saat itu Indonesia ketinggalan jauh dari dalam perencanaan tata kota dibandingkan Singapura. Belakangan saja, kemajuan tata kota Jakarta sudah cukup menghibur rasa ketertinggalan itu dan menjadi bekal perbandingan dalam kunjunganku saat ini.
Satu hal yang saya catat dari kunjungan saat ini adalah keterangan sopir mobil travel yang kami sewa. Ini masalah keberhasilan atau sesuatu hal lain. Sopir itu menceriterakan 80 % warga Singapore tinggal di rumah susun atau apartemen. Hanya orang yang memiliki kekayaan besar yang mampu tinggal dalam rumah sendiri. Gaji terendah warga Singapura adalah sekitar 20 Juta rupiah.
Warga Singapura rata-rata menginginkan anaknya melanjutkan studi perguruan tinggi dl luar negeri dan menginginkan mendapat pekerjaan nantinya juga di luar negeri. Tentu data ini menarik perhatian saya. Singapura dengan gayanya sendiri telah menjadikan warganya bekerja keras, ingin menjadi warga negara yang kompeten, berdaya saing.
Sekalipun juga saya mencatat kondisi paradoks bila membandingkan Singapura dengan Indonesia. Pemerintah Singapura berhasil mendorong warganya disiplin tinggi dan pekerja keras dan menghasilkan kesejahteraan hidup tingkat tertentu dengan membatasi iklim demokrasi politik dan menghindari ideologi yang berseberangan dengan pemerintah. Sementara di Indonesia warga mempunyai kebebasan demokrasi yang tinggi, warga bisa berlomba-lomba membikin partai politik baru, namun kebanyakan warga tertinggal dalam kehidupan ekonominya.
Di Singapura, warga negara dituntut lebih menjadi pekerja keras dan bisa hidup berkecukupan, namun dibatasi dalam artikulasi politiknya; sedangkan warga negara Indonesia mempunyai kebebasan dalam memproduksi wacana, namun terbatas dalam kemampuan penguasaan sumber daya dan finansialnya. Negeriku negeri wacana, pikirku.
Balik ke Jakarta, hari Sabtunya saya mendapat undangan menghadiri seminar Pendidikan di Rancamaya Islamic Boarding School di Bogor yang dihadiri para tokoh Pendidikan Indonesia. Beberapa nama beken hadir lewat zoom atau langsung seperti: Tri Suharti (Sekjen Kemdikbudristek), Kamarudin Hidayat (Rektor Universitas International Islam Indonesia), Laode Masihu Kamarudin (Rektor Universitas Insan Cita Indonesia), Amich AlHumami (Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas), Adlin Sila (Staf Ahli Kemendikbud), Trina Fizzanty (Kepala Pusrisdik, BRIN), Imam Tholhah (Kepala Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam/GUPPI) dan banyak pakar dan praktisi pendidikan yang lain yang hadir. Masing-masing menyuarakan apa yang menjadi perhatian penting dalam memajukan Pendidikan dan peradaban di Indonesia.
Di mulai Kamarudin Hidayat (Rektor UIII) yang mencoba menawarkan perlunya internasionalisasi Pendidikan karakter. Banyak orang asing takjub dengan kehidupan demokrasi dan agama di Indonesia. Dua orang Wanita, satu memakai baju dengan hijab bisa duduk bareng dengan wanita yang memakai rok mini makan bareng di satu meja. Bagi negara muslim tertentu ini cukup aneh. Namun di Indonesia itu pemandangan biasa. Model toleransi seperti ini sebenarnya menarik perhatian banyak negara. Sayangnya Indonesia belum banyak menyediakan beasiswa untuk studi perguruan tinggi untuk orang asing di Indonesia. Sementara kita orang Indonesia menikmati beasiswa bahkan dari negara yang lebih miskin dari Indonesia. Mudah-mudahan kehadiran UIII dapat menjadi terobosan dalam internasionalisasi Pendidikan karakter tersebut.
Amich Alhumami, Direktur Pendidikan Agama dan Pendidikan Bappenas, mengemukakan pentingnya kepedulian dunia Pendidikan agar mampu menggeser tingkat rata-rata anak usia sekolah tidak hanya pada pendidikan dasar, namun menggeser untuk lebih banyak anak usia belajar ke Pendidikan tinggi minimal ke jenjang Pendidikan menengah atas. Ini penting sebagaimana restorasi Jepang saat itu dan kebangkitan Tiongkok saat ini. Pilihan yang dilakukan kedua negara itu melakukan pengiriman anak muda untuk sebanyak-banyaknya untuk studi ke Barat. Pemikiran ini disadari walau semua pelajar itu ada resiko tidak semua akan kembali, pastilah dari berapapun yang Kembali, sebut misalnya hanya 1%, maka yang kecil ini akan memajukan Jepang untuk menyamai Barat. Dan itu terbukti dengan kemajuan Jepang dan Tiongkok saat ini.
Didin Safrudin, Dosen UIN Jakarta, agak berbeda dengan kebanyakan orang yang memuja peradaban barat, dia justru mengusulkan pentingnya membangun keilmuan dengan basis kearifan local. Menurutnya peradaban barat yang membangun pondasi peradabannnya berdiri atas nilai-nilai keluar dari kunkungan agama (sekulerisme), prestasi-prestasi dibangun dalam kontruksi kapitalistik (materialisme), dan kemajuan berdiri pada asas kebebasan (liberalisme) hari ini mulai pudar atau runtuh. Mereka kehilangan jiwa kemanusiaannya, teralineasi dan tidak tahu lagi kemajuan ini untuk siapa. Dia mengusulkan Indonesia jangan meneruskan gaya Barat yang saat ini mendekati kejumudannya, Indonesia perlu membangun keilmuan sebagai basis peradaban dengan mengangkat nilai-nilai local-kultural yang sesungguhnya dimiliki semua bangsa di dunia.
Iwan Pranoto (Guru Besar MIPA ITB) memaparkan pandangan kemajuan kecerdasan buatan atau artifisial intelligence (AI) saat ini jangan ditakuti. Biarkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak manusiawi digantikan oleh robot seperti kasir jalan tol, narik becak, mengepak barang. Biarkan pekerjaan itu digantikan oleh robot atau teknologi AI saat ini. Menurutnya masih banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin, hal itu yang menjadi tugas Lembaga pendidikan saat ini untuk membaca ruang-ruang tersebut. Pekerjaan-pekerjaan masa depan yang tidak bisa digantikan oleh mesin seperti konseling, guru, kiai, programmer, pemimipin dan sebagainya.
Sampai di sini, saya merasa semua pemikiran hebat-hebat dan betul juga, sampai saya merenung sejenak, kemudian gagasan apa yang bisa dilakukan untuk Indonesia. Sebuah gagasan dengan daya dongkrak kuat, radikal untuk secepatnya dapat memajukan peradaban Indonesia dalam waktu cepat. Waktu cepat misalnya 20 tahun (menuju Indonesia emas 2045); 50 tahun (Usia Indonesia 130 tahun); atau 100 tahun ke depan. Saya Kembali berpikir di Indonesia ini masing-masing pakar pintar berwacana, namun tumpul dalam berkreasi. Ya …kreasi yang dibutuhkan saat ini untuk mengubah secara radikal peradaban Indonesia, pikirku. Namun bukannya Ki Hajar Dewantoro sudah pernah mengusulkan perlunya mengembangkan daya cipta, rasa dan karsa dalam mengembangkan Pendidikan di Indonesia.
Tibalah saat tanggapan di forum seminar itu. Seorang penanggap dalam seminar mengingatkan bahwa dalam Al-Qur’an surat At Tin menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk sempurna-sempurnanya ciptaan. Namun mereka akan jatuh dalam derajat serendah-rendahnya, kecuali orang yang beriman. Menurutnya, Barat dibangun dengan mengenyampingkan persoalan iman kepada agama, setidaknya menjadikan agama masalah privat saja. Barang kali dari situ peradaban perlu dikembalikan kepada iman yang benar.
Ibu Aliya Rasyid (Ibunya Anies Baswedan), yang kebetulan juga hadir di seminar ini, memberi catatan bahwa dalam memajukan pendidikan di Indonesia ini perhatian pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan swasta masih kurang. Padahal Lembaga Pendidikan swasta di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Akibatnya sekolah-sekolah swasta kebanyakan masih tertinggal di belakang. Di samping itu, kebijakan Pendidikan di Indonesia sering bergonta-ganti kebijakan. Ganti Menteri ganti kebijakan.
Terhadap catatan yang kedua dari ibu Aliya Rasyid dan penanggap sebelumnya, saya sedikit memberi catatan agak nakal, gonta-gantinya kebijakan karena masing-masing pemikir sangat beriman (sangat yakin) dengan gagasannya masing-masing. Para pengambil kebijakan sangat meyakini gagasanya yang terbaik memperbaiki keadaan, pikirku. Karena itu, begitu mereka mempunyai kuasa atas birokrasi dunia pendidikan, mereka kepingin mengubah sistem pendidikan ke arah yang menurut keimanan atau keyakinan lebih baik.
Kayaknya mengembalikan persoalan sebatas keimanan saja tidak cukup, tambahku. Barangkali kita perlu melangkah yang kedua dari surat At Tin tadi, yaitu selain beriman perlu amal soleh. Amal yang soleh yang dimaksud adalah kerja yang berkualitas, kerja yang mempunyai nilai tambah, kerja yang mempunyai daya ubah. Untuk memberi muatan dan bukan sekedar teriak yang penting “kerja, kerja dan kerja.”
Amal yang berkualitas, pikiranku mulai menyimpul ke kata itu. Semua elemen bangsa perlu memikirkan dan beraksi atas kata itu. Kebetulan saat itu, salah satu peserta seminar adalah seorang Kepala Pusat riset Pendidikan, Trina Fizzanty. Dia sedang berfikir bahwa dunia riset, sebagai backbone peradaab ini perlu dibenahi. Riset saat ini belum menjadi nahkoda perubahan. Karenanya dia sedang mencoba mengerjakan program penguatan kultur riset di jenjang Pendidikan menengah, dengan program penguatan sekolah/madrasah riset. Mudah-mudahan semua pihak bisa bekerjasama, imbuhnya.
Hadir pula staf ahli Kemendibud, Adlin Sila. Dia diberi kesempatan untuk menanggap. Dia memberi informasi, seiring dengan gagasan pak Amich Al Humami, kemendikbudristek hari ini setiap tahun menargetkan atau membiayai 3500 calon doctor. Dengan demikian setiap tahunnya kita berharap jumlah doctor di Indonesia bertambah siginifikan. Wah Kementerian Agama, kalua gitu sudah mengambil Langkah yang benar, pikirku. Kemenag menggagas 5000 doktor. Gagasan yang waktu launching dianggap terlalu ambisius. Saat ini nampaknya jumlah 5000 doktor itu belum sepenuhnya tercapai.
Kembali ke gagasan amal salih, nampaknya saya merasa perlu untuk mengekplorasi lebih lanjut. Kultur riset di Indonesia belum berada di posisi sentral. Semua Lembaga Pendidikan tinggu menuntut riset sebagai kompetensi para lulusannya. Para dosen juga dituntut untuk terus melakukan riset. Namun riset terkesan hanya sebagai ritual akademis saja. Belum terasa perubahan signifikan dalam dunia riset kita. Hal ini ditandai dengan masih minimnya jumlah paten dan publikasi global bereputasi dari bangsa Indonesia.
Saya sebagai peneliti, sedikit mengakui bahwa kita telah banyak melakukan riset. Riset yang dibiayai negara tentunya. Namun penelitian kami juga masih sedikit yang menembus paten dan publikasi global bereputasi. Banyak yang berpikiran, nasib kami para peneliti sedang dipaksa mengikuti kebijakan baru untuk bergabung dalam sebuah Lembaga/kementerian, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Banyak peneliti hari ini beranggapan, kami peneliti jadi korban politik. Peneliti dikumpulkan namun dibatasi, atau diseleksi ketat untuk mendapatkan pekerjaan penelitian. Walau di satu sisi, tukin kami diberikan secara penuh.
Di tengah ruang penelitian yang sempit, saya kebetulan dua tahun berturut-turut termasuk yang berhasil memenangkan kompetisi lelang riset di antara para peneliti. Walau dana yang tersedia sangat minim. Ya lumayanlah untuk mengisi kekosongan. Sementara waktu, mencari kegiatan di kementerian, hari ini birokrasi kementerian masih banyak yang sakit hati, kalau tidak kecewa, dengan sikap peneliti yang lebih memilih meninggalkan kementerian, dari bertahan di Kementerian. Akibatnnya ada hambatan-hambatan komunikasi.
Sempitnya mencari sponsor kegiatan penelitian, membuat teman-teman peneliti mulai menjajagi kerjasama ke segala arah, mana yang mungkin. Selain dengan kementerian, mereka mencoba mendekati pemerintah-pemerintah daerah, atau perusahaan-perusahan tertentu untuk bisa mengembangkan dana CSR nya. Sebagian teman berhasil mendapatkan, walau banyak juga yang belum menemukan bentuk. Namun di sisi lain, dibalik sengsara saya mencoba memaknai untuk mencari hikmahnya. Hari ini dengan kondisi ini saya menjadi semakin inten membuka peluang kolaborasi dengan dosen-dosen kampus yang mempunyai reputasi global, menghubungi kenalan peneliti luar negeri. Nampaknya kalau ditekuni ada juga mulai terlihat peluang-peluang kolaborasi di dunia penelitian baik dalam maupun luar negeri.
Dari komunikasi berbagai pihak itu, saya juga kemudian mendapatkan kesempatan mengisi acara di sana sini, untuk menjadi narasumber dalam penguatan riset di perguruan tinggi, diundang dalam kegiatan Pemda, bahkan diundang khutbah segala. Di dunia kampus, saya membayangkan juga kenapa juga riset-riset di berbagai perguruan tinggi tidak berkembang ideal. Saya sampai pada kesimpulan, karena penelitian di kampus-kampus belum menemukan ekosistem yang pas. Ya ekosistem yang pas. Mungkin beberapa peneliti, pelan-pelan mulai mengintip dan mendapatkan ekosistem yang pas ini. Ekosistem untuk mendapatkan hasil riset yang berkualitas, kolaborasi sesama profesi peneliti, dan meraih publikasi global. Kalua para peneliti baru mulai mendapatkan ekosistem yang dibutuhkan bagaimana nasib ribuan dosen perguruan tinggi itu mendapatkan ekosistem itu? Itulah problematika perguruan tinggi yang hingga saat ini di bidang risetnya belum menjadi ekosistem yang memadai. Demikian juga di bidang Pendidikan, ekosistem apa yang dibutuhkan.
Bicara tentang ekosistem, barangkali gagasan ekosistem itu levelnya berada kebijakan mikro (kecil), atau mezzo (menengah). Tapi yang jelas bukan pada level makro (tinggi/besar). Terus apa yang dibutuhkan dalam mewujudkan ekosistem itu. Saya kemudian berusaha mengeja. Nampaknya ada tiga hal untuk mewujudkan ekosistem itu, yaitu kompetensi, kolaborasi dan integritas. Kompetensi berarti kita harus menguasai betul dunia yang kita geluti. Kolaborasi berarti kita perlu mengembangkan Kerjasama dengan pihak-pihak yang mempunyai bidang garap yang sama. Integritas, berarti kita harus yakin dengan dunia yang kita geluti dan terus kreatif mengembangkannya.
Sebagai penutup. Demikian juga dengan dunia pendidikan yang perlu menemukan dan mewujudkan ekosistem yang baik dalam memberikan layanan. Sebuah Lembaga Pendidikan hendaknya mampu mengantarkan anak didik secara maksimal. Gagasaan Lembaga Pendidikan yang multi talent akan menjadi alternatif yang baik, dari pada Lembaga Pendidikan yang hanya sekedar mengeluarkan sertifikat saja. Semua pihak perlu berfikir mewujudkan ekosistem yang baik di setiap levelnya, baik itu di tingkat satuan pendidikan maupun dalam kepengurusan GUPPI di tiap levelnya. Dirgahayu GUPPI ke 73, semoga GUPPI semakin jaya.
Murtadlo/diad