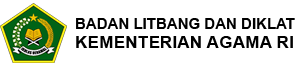Fleksibilitas Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Widyaiswara Pasca Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2025

Jakarta (BMBPSDM)---Pernahkah membayangkan bisa menyelesaikan pekerjaan sambil menikmati suasana rumah? Konsep ini bukan lagi khayalan. Di era serba digital, fleksibilitas kerja telah menjadi kebutuhan, bukan sekadar tren. Perusahaan-perusahaan besar dunia seperti Google dan Microsoft sudah lama menerapkan flexible work arrangement (FWA). Namun, di Indonesia, khususnya di instansi pemerintah, konsep ini baru benar-benar mengemuka di tahun 2025.
Awalnya, fleksibilitas kerja di lingkungan pemerintah muncul sebagai respons terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dan dengan Surat Edaran Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Kerja saat Idulfitri. Selain itu, juga merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Kemudian, aturan ini diperkuat dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan PNS secara Fleksibel. Hadirnya regulasi ini membuka pintu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk widyaiswara, untuk bekerja lebih dinamis --tidak lagi terikat pada ruang fisik.
Namun, di lapangan, implementasinya tidak semudah membalik telapak tangan. Di lingkungan Kementerian Agama sendiri, misalnya, fleksibilitas kerja lebih banyak dilihat sebagai upaya efisiensi anggaran. Hal ini seperti tertuang dalam SE Sekjen Kemenag No. SE.12 Tahun 2025. Boleh jadi karena masih merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025, daripada sebagai strategi peningkatan produktivitas. Padahal, seharusnya semangat yang dikedepankan bukan sekadar penghematan, melainkan transformasi budaya kerja yang lebih adaptif dan manusiawi.
WFH atau "Libur Tambahan"? Tantangan Mindset di Balik Fleksibilitas
Masih terngiang ucapan rekan kerja. "Kalau WFH, paling tidak hemat ongkos dan dapat mengerjakan hal lain di rumah," katanya sambil tertawa. Seperti lucu, tapi hal ini menggambarkan sebuah masalah serius. Fleksibilitas kerja masih sering disalahartikan sebagai "libur tambahan.”
Padahal, dengan teknologi seperti zoom, google meet, dan berbagai platform kolaborasi daring, seharusnya koordinasi antarpegawai bisa lebih lancar. Namun, faktanya, masih terdapat keluhan sulit berkomunikasi saat bekerja jarak jauh. Di sini, masalah utamanya bukan pada teknologi, melainkan pada mindset.
Fleksibilitas kerja sejatinya adalah tentang tanggung jawab, bukan kebebasan tanpa batas. Di sektor swasta, perusahaan-perusahaan sudah menerapkan key performance indicators (KPI) yang jelas untuk memastikan pekerja tetap produktif meski tidak di kantor. Lalu, mengapa di instansi pemerintah hal ini masih menjadi tantangan?
Widyaiswara di Tengah Arus Perubahan: Antara Peluang dan Dilema
Sebagai widyaiswara dengan pengalaman 19 tahun yang terlibat dalam pelatihan ASN, saya melihat betapa widyaiswara memiliki peran strategis dalam transformasi ini. Dengan perkembangan e-learning, widyaiswara kini bisa mendesain materi pelatihan, memberikan pengajaran, dan berdiskusi dengan peserta tanpa harus bertatap muka langsung.
Namun demikian, di lingkungan BMBPSDM Kemenag RI ada wacana yang menarik, yaitu rencana penempatan widyaiswara ahli utama di Pusbangkom. Di satu sisi, hal ini sesuai dengan jenjang tugas dan fungsi widyaiswara ahli utama dengan level pelatihan jenjang tinggi. Sekaligus bisa mempermudah koordinasi. Tapi di sisi lain, bukankah ini seperti bertentangan dengan semangat Permenpan RB No. 4/2025 yang justru memberi ruang untuk kerja fleksibel? Terutama seperti dijelaskan dalam BAB II pasal 12.
Bayangkan jika seorang widyaiswara ahli di bidang tertentu harus pindah ke Jakarta hanya karena aturan penempatan, padahal ia juga bisa berkontribusi maksimal dari daerah asalnya dengan dukungan teknologi. Apakah ini tidak justru kontraproduktif?
Untuk suksesnya implementasi fleksibilitas kerja di pemerintahan, termasuk bagi widyaiswara maka diperlukan beberapa langkah. Pertama, pentingnya sosialisasi yang menyeluruh. Bukan sekadar sosialisasi aturan, tapi juga perubahan paradigma. Fleksibilitas harus dipahami sebagai bentuk kepercayaan, bukan kelonggaran. Artinya, sosialisasi ini benar-benar membentuk paradigma baru dalam bekerja. Bukan dianggap sebagai tambahan waktu senggang di luar kantor yang bermuara pada pemanfaatan di luar tugas.
Kedua, perlunya penyediaan infrastruktur digital. Instansi pemerintah harus memperkuat jaringan internet, menyediakan platform kolaborasi, dan memberikan pelatihan teknologi bagi ASN. Selain itu, juga dukungan perangkat teknologi itu sendiri bagi pegawai agar mereka benar-benar optimal dan berkinerja ketika tidak di kantor.
Ketiga, membangun sistem penilaian yang adil. Ukuran kinerja harus beralih dari "kehadiran fisik" ke "kontribusi nyata.” Seorang widyaiswara bisa dinilai dari kualitas materi pelatihan yang dibuat, bukan dari jam kerja di kantor.
Terakhir, keempat, implementasi kebijakan yang konsisten. Jangan sampai ada aturan yang saling bertolak belakang. Jika fleksibilitas tempat kerja sudah diatur dalam Permenpan RB, maka kebijakan teknis di kementerian harus sejalan.
Pada akhirnya, perubahan selalu menimbulkan ketidaknyamanan. Tapi seperti kata bijak, "Kapal paling aman adalah yang selalu tertambat di pelabuhan, tapi bukan untuk itu kapal dibuat."
Fleksibilitas kerja bukan sekadar tentang boleh tidaknya bekerja dari rumah atau tempat lain yang ditentukan. Ini tentang bagaimana kita sebagai bangsa siap menghadapi era baru --di mana batas fisik bukan lagi penghalang untuk berkontribusi.
Bagi widyaiswara, momen ini adalah kesempatan emas untuk menulis babak baru dalam pengembangan SDM ASN. Dengan semangat adaptasi dan kreativitas, saya yakin kita bisa membuat fleksibilitas kerja benar-benar bermakna --bukan hanya di atas kertas, tapi dalam praktik nyata.