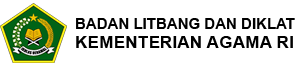Pokok-Pokok Pendapat Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar

POKOK-POKOK PENDAPAT PROF. DR. H. M. ATHO MUDZHAR
AHLI DALAM SIDANG PERKARA UJI MATERIL UU NO.1/PNPS/1965
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
REGISTER PERKARA NO. 140/PUU-VII/2009 TANGGAL 28 OKTOBER 2009
di Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat
Tanggal 17 Februari 2010
Assalamualaikum wr. wb.
Yang kami muliakan, Ketua dan para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,
Para hadirin sekalian yang kami hormati.
Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa pokok pikiran atau
pendapat saya dalam Sidang Perkara Uji Materil UU No.1/PNPS/1965 ini, yaitu
sebagai berikut:
1. UU No.1/PNPS/1965 dan keadaan darurat.
Undang-Undang (UU) No.1/PNPS/ 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama semula adalah Penetapan Presiden yang
dikeluarkan pada tahun 1965, kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi UU
dengan UU No. 5 Tahun 1969. Dengan demikian, apa yang kemudian disebut
sebagai UU No.1/PNPS/1965 itu sesungguhnya diundangkan pada tahun 1969,
pada saat mana negara tidak dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, UU
tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang dan sah secara hukum serta
mengikat bagi setiap warga negara.
2. UU No.1/PNPS/1965 dan masalah intervensi negara terhadap agama.
Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama, menyatakan sebagai berikut:
Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan
atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu
agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang
menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan
mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
Secara sepintas, rumusan Pasal 1 ini memberi kesan seolah-olah UU ini
mengatur tentang kebolehan intervensi Pemerintah atau negara terhadap agama
atau terhadap keyakinan warga masyarakat, sehingga memasuki forum internum
kebebasan beragama. Sesungguhnya apabila kita perhatikan penjelasan UU itu
2
yang merupakan suatu kesatuan dengan batang tubuh UU-nya, maka kita akan
memahami bahwa UU No.1/PNPS/1965 hanya mengatur forum externum
kebebasan beragama karena tujuan UU ini bukanlah untuk intervensi Pemerintah/
negara terhadap agama, atau aspek-aspek doktrin agama, atau penafsiran
agama, melainkan bertujuan untuk memupuk dan melindungi ketentraman
beragama sebagaimana disebut pada Butir 4 Penjelasan Umum UU tersebut.
Dengan kata lain, UU ini adalah bagian dari upaya negara atau Pemerintah untuk
mencegah terjadinya benturan umat beragama dan memelihara ketentraman serta
ketertiban masyarakat yang dapat terganggu karena adanya polarisasi dan pertentangan
dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan yang
menyimpang. Bahkan pada Butir 2 dan 3 Penjelasan Umum UU tersebut
ditegaskan bahwa UU itu diperlukan untuk memelihara persatuan nasional dan
persatuan bangsa. Tentu saja, tugas Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat serta pemeliharaan persatuan dan kesatuan nasional adalah tugas dan
kewajiban negara yang sah dan legal.
Hal itulah sebenarnya yang dilakukan Pemerintah ketika menerbitkan Surat
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam
Negeri RI, Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor: 199
Tahun 2008, tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau
Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat,
tanggal 9 Juni 2008. SKB itu pada intinya memperingatkan dan memerintahkan
kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI, sepanjang mengaku
beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran paham atau penafsiran agama
yang nyata-nyata telah menimbulkan polarisasi dan pertentangan dalam masyarakat
sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. SKB itu juga
memperingatkan dan memerintahkan warga masyarakat pada umumnya untuk
menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban
kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan
melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI.
Bagi Pemerintah, nampaknya masalah JAI ketika itu mempunyai dua aspek
pertimbangan. Pada satu sisi, JAI sebagai penyebab lahirnya pertentangan dalam
masyarakat yang berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pada sisi lain, warga JAI ketika itu adalah korban tindakan kekerasan sebagian
3
masyarakat, yang karenanya harus dilindungi. Untuk menangani kedua sisi
masalah itu secara simultan maka Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam
Negeri mengeluarkan SKB tersebut pada tanggal 9 Juni 2008. Perlu dicatat, bahwa
dasar kebijakan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan melindungi kelompok
masyarakat JAI itu adalah UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama ini. Dengan pertimbangan tersebut di atas
maka UU No.1/PNPS/1965 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan secara
yuridis serta sosiologis masih relevan dengan tugas-tugas kenegaraan.
3. UU No.1/PNPS/1965 sebagai penyelamat umat Khonghucu di Indonesia.
Seperti diketahui, meskipun Khonghucu adalah salahsatu dari 6 agama yang
disebutkan dalam UU No.1/PNPS/1965 tetapi umat Khonghucu Indonesia pada
suatu masa telah dibatasi ruang geraknya oleh Instruksi Presiden RI No. 14 Tahun
1967, sehingga mereka tidak dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan,
kepercayaan, dan adat istiadat mereka di muka umum. Sebagai akibatnya,
sebagian mereka kemudian bergabung dengan salahsatu dari 5 agama lainnya,
baik dalam kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat, maupun dalam
pencantuman identitas agama dalam Kartu Tanda Penduduk dan sebagainya,
(meskipun mungkin mereka masih tetap memeluk agama Khonghucu). Hal ini
berlangsung selama 33 tahun, yaitu sejak tahun 1967 hingga 2000. Pada tahun
2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6
Tahun 2000, yang pada intinya menetapkan pencabutan larangan sebagaimana
diatur oleh Inpres No. 14 Tahun 1967 tersebut. Dengan pencabutan ini, maka
secara legal pembatasan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat
Cina di Indonesia tidak berlaku lagi.
Pada Tahun 2002, dengan Kepres No. 19 Tahun 2002, Tahun Baru Imlek
dinyatakan sebagai Hari Nasional. Kemudian pada tahun itu juga (2002), Menteri
Agama RI dengan Surat Keputusan No. 331 tahun 2002 menyatakan bahwa Hari
Raya Imlek ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Tetapi dengan penetapan Hari
Raya Imlek sebagai hari libur nasional itu pun masih belum serta-merta umat
Khonghucu memperoleh kebebasan beragama dan hak-hak sipil mereka, karena
masih ada pendapat dalam masyarakat bahwa Hari Raya Imlek bukanlah milik
umat Khonghucu semata tetapi adalah milik seluruh masyarakat keturunan
Tionghoa. Kemudian perlu dicatat bahwa hak beragama umat Khonghucu dan
4
hak-hak sipil mereka itu baru terpenuhi secara faktual setelah Menteri Agama RI
mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan
Nasional dengan Nomor: 12/MA/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Penjelasan
mengenai Status Perkawinan Menurut Agama Khonghucu dan Pendidikan Agama
Khonghucu, yang menyatakan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan UU No. 1 PNPS 1965 Pasal 1 Penjelasan dinyatakan bahwa
agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, dan Khonghucu (Confusius). Sebagaimana diketahui UU tersebut
sampai saat ini masih berlaku dan karena itu Departemen Agama melayani umat
Khonghucu sebagai umat penganut agama Khonghucu. Selanjutnya berkaitan
dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan
bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu, maka Departemen Agama memperlakukan perkawinan
para penganut agama Khonghucu yang dipimpin pendeta Khonghucu
adalah sah menurut Pasal 2 ayat (1) tersebut.
2. Berkaitan dengan butir 1 tersebut di atas, maka pencatatan perkawinan bagi para
penganut agama Khonghucu dapat dilakukan sesuai peraturan perundangan yang
ada. Demikian pula hak-hak sipil lainnya.
3. Berkaitan dengan butir 1 di atas kami (Menteri Agama) berpendapat bahwa
pendidikan agama Khonghucu sesuai dengan ketentuan pasal 12a UU No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal ini Departemen Agama ke
depan akan memfasilitasi penyediaan guru-guru pendidikan agama Khonghucu di
sekolah-sekolah. ..dst.
Sejak keluarnya Surat Menteri Agama Nomor: 12/MA/2006 tanggal 24
Januari 2006 itulah umat Khonghucu di Indonesia secara faktual memperoleh
kebebasan menjalankan agama dan hak-hak sipil mereka. Perlu dicatat, bahwa
dasar hukum yang dijadikan pijakan oleh Menteri Agama dalam menerbitkan surat
tanggal 24 Januari 2006 itu adalah UU No.1/PNPS/1965, yang menurut Surat
Mahkamah Konstitusi Nomor: 356/PAN.MK/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005,
yang ditujukan kepada Saudara Ws. Budi S. Tanuwibowo, Majelis Tinggi Agama
Khonghucu Indonesia (MATAKIN), menyatakan bahwa Undang-Undang No.
1/PNPS/1965 jo UU No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2727) masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UU No.1/PNPS/1965 adalah penyelamat
hak beragama dan hak-hak sipil umat Khonghucu di Indonesia, dan
karenanya UU ini tidak bertentangan dengan UUD 1945.
5
4. UU No.1/PNPS/1965 sebagai pijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU No.1/PNPS/1965
pada butir 3 dan 4, salahsatu tujuan penerbitan UU itu adalah agar ketentraman
beragama dapat dinikmati oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia, dan
untuk melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/ penghinaan.
Dengan kata lain, UU ini diterbitkan dengan tujuan antara lain untuk memelihara
kerukunan umat beragama, baik kerukunan internal umat beragama maupun
antarumat beragama. Sebagai aturan hukum, UU ini telah dijadikan dasar oleh
para hakim di Pengadilan dalam memutus perkara-perkara yang terkait dengan
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Keputusan-keputusan hakim itu
telah menjadi kekuatan hukum tetap dan telah secara efektif berfungsi memelihara
kerukunan umat beragama, bukan saja umat Islam, tetapi juga umat beragama
lainnya. Sejumlah keputusan pengadilan yang telah diterbitkan tersebut, antara
lain: Putusan Hakim Pengadilan dalam Kasus Arswendo Atmowiloto, Kasus Saleh
di Situbondo (1996, dikenai Pasal 156a), Kasus Mas’ud Simanungkalit (2003,
dikenai Pasal 156a), Kasus Mangapin Sibuea, Pimpinan Sekte Pondok Nabi
Bandung (2004, dikenai Pasal 156a), Kasus Yusman Roy (2005, dikenai Pasal
335 dan 157 KUHP), Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.677/PID.B/ 2006/ PN.JKT.PST, tanggal 29 Juni 2006 dalam perkara Lia Eden,
Kasus Abdurrahman yang mengaku Imam Mahdi, Kasus penistaan kitab suci di
Malang (2006, dikenai Pasal 156a), dan puluhan keputusan pengadilan tentang
perkara penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di Nusa Tenggara Timur,
yakni terkait perkara-perkara penodaan roti suci (hostia) di lingkungan umat
beragama Katolik. Khusus putusan-putusan pengadilan yang disebut terakhir ini
mungkin luput dari pengamatan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) atau
dipandang tidak berhubungan dengan peran UU No.1/PNPS/1965 dalam
pemeliharaan kerukunan umat beragama di NTT.
Dengan demikian, UU No.1/PNPS/1965 telah terbukti berhasil memelihara
kerukunan antarumat beragama dan juga kerukunan internal umat beragama, baik
Islam, Kristen, maupun Katolik. Karena itu UU No.1/PNPS/1965 tidak bertentangan
dengan UUD 1945.
6
5. UU No.1/PNPS/1965 dan masalah diskriminasi.
Mengenai pendapat yang mengatakan bahwa UU No.1/PNPS/1965 adalah
diskriminatif karena membatasi agama hanya pada enam agama, yaitu: Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, adalah pendapat yang tidak
benar. Memang pada Penjelasan Pasal 1 paragraf pertama UU itu dikatakan
sebagai berikut: "Agama-agama yang dipeluk oleh Penduduk Indonesia ialah:
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat
dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia." Tetapi
kemudian dalam paragraf ketiga Penjelasan Pasal 1 itu juga, secara eksplisit
disebutkan sebagai berikut: "Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya:
Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Thaoism, dilarang di Indonesia. Mereka mendapat
jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 (UUD 1945),...dst."
Perlu dicermati di sini bahwa baik ketika menyebutkan enam agama tersebut
di atas maupun ketika menyebutkan agama-agama lainnya, Penjelasan Pasal 1
itu menyebutkan bahwa kedua jenis kelompok agama itu mendapat jaminan
seperti yang diberikan oleh Pasal 29 UUD 1945. Bahkan ketika menyebut agamaagama
lainnya selain yang enam tersebut, Penjelasan itu secara eksplisit
menyatakan bahwa jaminan itu bersifat penuh. Karena itu, UU No.1/PNPS/1965
tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Prinsip kebebasan beragama seperti dianut UU ini seringkali tidak dipahami
oleh masyarakat, baik nasional maupun internasional. Sebagai contoh, terjadi
dalam dialog bilateral Hak Asasi Manusia (HAM) antara Indonesia dan Norwegia
di Oslo tanggal 26-29 April 2009, pada Komisi Interfaith Dialogue and Religious
Tolerance. Pada awal sidang-sidangnya, dalam komisi itu dilaporkan hasil sidang
serupa pada tahun sebelumnya (2008) yang menyatakan antara lain bahwa UU
No.1/PNPS/ 1965 perlu dicabut karena UU itu dinilai membatasi hanya pada enam
agama. Mendengar hal itu, saya (kebetulan ketika itu menjadi salahseorang
anggota Delegasi RI dalam forum itu) mengajak peserta dialog HAM bilateral itu
untuk membaca dengan seksama Penjelasan Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965.
Setelah diskusi secara seksama, Komisi itu menyimpulkan bahwa agama-agama
di luar agama yang enam juga boleh hidup dan mendapat dukungan konstitusional
yang sama di Indonesia. Akhirnya, Komisi itu merekomendasikan perlunya sosialisasi
kesadaran bahwa agama-agama di luar yang enam itu boleh dan mempunyai
7
hak hidup di Indonesia. Tepatnya hasil rumusan Working Group itu dimuat pada
Butir 4 yang berbunyi sebagai berikut: "Socialization/raising public awareness of
existence of more than 6 religions, and that all religions are acknowledged. All
religions and beliefs are equally guaranteed by the Indonesian Constitution."
6. Kebebasan Hak Asasi Manusia Dibatasi oleh Undang-Undang.
Sebagaimana diketahui, UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 menyatakan
sebagai berikut:
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Kemudian dalam Amandemen-amandemen berikutnya, telah ditambahkan
Pasal 28E, yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak
kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran
dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat.
Kemudian juga ditambahkan Pasal 28I, yang berbunyi sebagai berikut:
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Setelah itu, ditambahkan pasal 28J yang menyatakan sebagai berikut:
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.
Perlu digarisbawahi di sini bahwa pembacaan pasal-pasal itu hendaknya dilakukan
secara menyeluruh. Orang tidak boleh hanya membaca Pasal 29, 28E, dan
berhenti pada Pasal 28I saja, melainkan harus juga membaca Pasal 28J sebagai
satu kesatuan dengan pasal-pasal sebelumnya.
8
Adanya pembatasan-pembatasan itu tidak perlu mengecilkan hati kita
seolah-olah kita adalah bangsa yang tidak memiliki kebebasan beragama. Hal itu
dimungkinkan sepanjang dilakukan melalui undang-undang, semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan dan ketertiban umum.
Sesungguhnya dalam instrumen-instrumen internasional pun hal serupa
memang diatur. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal
Declaration of Human Rights) yang diadopsi PBB pada tahun 1948, Pasal 29 Ayat
(2), dikatakan sebagai berikut:
In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such
limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition
and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of
morality, public order and the general welfare in a democratic society.
(dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang hanya patuh kepada
pembatasan yang diatur melalui undang-undang, semata-mata untuk tujuan menjamin
pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk
memenuhi tuntutan moralitas yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum
dalam suatu masyarakat demokratis).
Dalam Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (diadopsi
PBB Tahun 1966) yang telah kita ratifikasi menjadi UU No. 12 Tahun 2005, Pasal
18 Ayat (3) berbunyi sebagai berikut:
(3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya
dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi
keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan
mendasar orang lain.
Kemudian dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk
Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan (Declaration on the
Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion
and Belief) Tahun 1981, pada Pasal 1 Ayat (3) juga dinyatakan sebagai berikut:
Freedom to manifest ones religion or beliefs may be subject only to such limitations as
are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals,
or the fundamental rights and freedoms of others.
(Kemerdekaan seseorang untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya hanya
dapat dibatasi oleh UU dan dalam rangka menjamin keselamatan umum, ketentraman
umum, kesehatan umum, atau nilai-nilai moral atau hak-hak dasar dan kebebasan
orang lain)
9
Demikian juga dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh
Sidang Umum PBB yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1989
(Convention on the Rights of the Child), dalam Pasal 14 ayat (3) dinyatakan
sebagai berikut:
Freedom to manifest ones religion or beliefs may be subject only to such limitations as
are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals,
or the fundamental rights and freedoms of others.
(Kebebasan seseorang untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya hanya
dapat dibatasi oleh UU dan dalam rangka untuk melindungi keselamatan, ketentraman,
kesehatan, dan nilai-nilai moral publik, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain).
Dengan demikian, Pasal 28J UUD 1945 sesungguhnya juga sejalan
dengan berbagai instrumen internasional yang telah diadopsi dan ditandatangani
oleh PBB. Dalam hal ini maka apabila UU No.1/PNPS/1965 itu dipandang sebagai
salahsatu pembatasan yang dilakukan dengan UU, maka hal itu sebenarnya
adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena adanya peluang yang
diberikan oleh Pasal 28J UUD 1945 itu yang harus dibaca sebagai bagian tak
terpisahkan dari pasal-pasal lainnya.
7. Penodaan agama sebagai isu internasional
Masyarakat internasional memang terbelah sedikitnya menjadi dua kelompok
terkait isu penodaan agama. Sebagian kelompok masyarakat mengatakan bahwa
pernyataan penodaan/ penistaan terhadap agama adalah bagian dari kebebasan
berekspresi. Mereka berpendapat bahwa yang seharusnya dilarang bukanlah
penodaan/penistaan agama, melainkan penistaan terhadap manusia. Kelompok
ini berpendapat bahwa menodai agama hanyalah menodai sesuatu benda di luar
manusia, karenanya tak perlu berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban
masyarakat. Adapun kelompok kedua berpendapat bahwa penodaan agama adalah
bagian dari penodaan/penistaan terhadap manusia, karena penodaan/ penistaan
agama tidak dapat dilepaskan dari penodaan/penistaan terhadap manusia pemeluk
agama itu sendiri. Di sinilah letak perbedaannya. Sesungguhnya kita bangsa
Indonesia sebagai masyarakat yang religius cenderung memilih pendapat kelompok
kedua. Dalam hubungan ini kita ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada
kelompok pertama, seperti: apakah kalau seseorang menghina milik orang lain itu
tidak berarti menghina si pemiliknya? Apakah bila seseorang menghina rumah
tempat tinggal seseorang, tidakkah dengan sendirinya ia menghina pemilik atau
10
orang yang menempati rumah itu? Apabila seseorang menista suatu ras/suku,
apakah orang itu tidak dengan sendirinya menista pemilik ras/suku tersebut? Dan
seterusnya. Apalagi agama, sesuatu yang bukan hanya dimiliki manusia, tetapi juga
dimuliakan dan disucikan. Oleh karena itu, penodaan/penistaan agama adalah
dengan sendirinya menjadi penodaan/penistaan terhadap manusia pemeluk agama
itu. Karena itu pula maka masalah penodaan/penistaan agama secara langsung
menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga
negara perlu turun tangan dan memberikan rambu-rambunya.
Dalam kaitan ini, menarik dicermati butir 13 dari hasil kesepakatan Durban
Review Conference, sebuah forum seminar resmi PBB yang diselenggarakan di
Jenewa pada bulan April 2009, yang menyatakan sebagai berikut:
Reaffirms that any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes
incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law; ....
(menegaskan bahwa setiap anjuran kebencian karena rasa kebangsaan, ras, atau
agama, yang mendorong kepada diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus
dilarang dengan undang-undang; …dan seterusnya).
Dokumen Durban Review Conference ini sesungguhnya merupakan perkembangan
baru dan pemahaman baru dalam kehidupan internasional, karena
dokumen itu sesungguhnya secara substantif telah mengakomodasi ide tentang
perlunya menghindari penodaan/penistaan agama (religious blasphemy atau
religious defamation), hanya saja dengan menggunakan istilah lain yaitu incitement
of hatred (pengobaran kebencian) berdasarkan agama. Sedangkan dalam
Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965 (atau Pasal 156a KUHP) digunakan istilah permusuhan,
penyalahgunaan, atau penodaan agama. Apalagi tadi pagi telah disebutkan
bahwa Sidang Majelis Umum PBB mengajak masyarakat internasional untuk
memerangi penodaan agama atau religious defamation. Nampaknya masyarakat
internasional telah bergeser sehingga semakin memahami bahwa penodaan
agama dapat berakibat langsung terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
Demikianlah beberapa pendapat yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini.
Atas perhatian Ketua dan para Anggota Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu ‘alaikum wr. wb.
Jakarta, 17 Februari 2010
ttd.
Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar