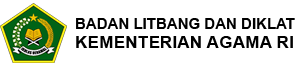Potret Sejarah Hubungan Umat Beragama di Maluku: Refleksi Singkat Seorang Peneliti

Secara umum, Maluku merupakan kawasan dengan percampuran etnik, sosio-kultur, dan politik antara Melanesia, Melayu, Jawa (Sanskrit), Arab, Persia, Cina, hingga Eropa. Pengaruh Arab, Persia, dan Melayu cukup kental di Utara. Pengaruh Arab, Melayu, dan utamanya Eropa cukup memberikan pengaruh di Wilayah Tengah dan Tenggara selain tentu saja pengaruh dari Wilayah Utara. 4 Kerajaan (Maloko Kie Raha), khususnya Ternate dan Tidore merupakan pusat politik dan sosio-kultur yang membentuk persekutuan Uli Lima (Ternate) dan Uli Siwa (Sembilan). Wilayah Tengah dan Tenggara secara politik terdiri atas wilayah-wilayah kecil ”berdaulat” (otonom) yang disebut negeri (Tengah) dan ohoi (Tenggara). Secara politik kedua wilayah tersebut memperoleh pengaruh persekutuan politik dari Utara dan tegabung dalam ikatan konfederasi patasiwa-patalima (Tengah) dan rat-schaap lorsiu-lorlim (Tenggara). Secara kultur masing-masing wilayah merupakan satu kesatuan kultur dengan beberapa identitas dan mekanisme kultur yang khas. Identitas kultur menjadi penanda kesatuan sub-etnik dan mekanisme kultural menjadi pendekatan efektif dalam penyelesaian persoalan-persoalan sosial yang terjadi.
Sejak masuknya agama-agama besar (Islam, Kristen, dan Katolik) di Kepulauan Maluku, agama kemudian diterima menjadi identitas etno-kultur dan sosio-politik meski dengan wajah dan bentuk ekspresi yang beragam. Agama terlebih dahulu masuk di Wilayah Utara (abad 14-15) dan bertransformasi menjadi kekuatan politik (kesultanan), Wilayah Tengah (abad 16-17)–dengan penanda Masjid Tua Wapauwe dan Gereja Immanuel di Jazirah Leihitu –yang mensegregasi kesatuan sosio-politik berdasarkan agama, dan yang terakhir Wilayah Tenggara yang dipenetrasi oleh 3 agama (Islam, Kristen, dan Katolik) antara abad 18-19. Segregasi sosio-politik di Tenggara karena perbedaan agama tidak sebagaimana di Wilayah Tengah. Islam menjadi agama dominan di wilayah Utara, Islam dan Kristen menjadi 2 agama yang hampir berimbang di Wilayah Tengah, Kristen dan Katolik menjadi agama yang lebih dominan di Tenggara dibandingkan islam
Di Wilayah Utara pengaruh Islam sebagai identitas etno-kultur dan politik cukup dominan, meski terdapat populasi umat Kristen yang cukup signifikan bahkan dominan di Halmahera Utara dan Barat. Wilayah Tengah keberterimaan agama melahirkan diferrensiasi soiso-kultur dan politik antara negeri Muslim dan negeri Kristen, meski antar negeri yang berbeda agama tersebut disatukan oleh ikatan persaudaraan geneologis dan politis melalui gandong dan pela, namun ikatan keduanya hanya mengikat lokus antar negeri yang terbatas. Di Wilayah Tengah ikatan keagamaan kerap lebih kuat dibandingkan ikatan geo-etnik sebagai sesama anak negeri. Wilayah Tenggara, ikatan kekerabatan cenderung lebih kuat dari ikatan keagamaan, kita akan sangat mudah menemukan orang yang tinggal di ohoi yang sama dan memiliki nama marga yang sama namun terdiri atas 3 agama, hal yang nyaris mustahil kita temukan di Wilayah Tengah. Sebelum kerusuhan pola pemukiman di Maluku tidak dengan segregasi yang ketat, akan kita temukan pemukim Muslim di wilayah Kristen maupun sebaliknya. Kerusuhan yang terjadi antara 1999-2002 telah benar-benar membuat diferensiasi dan segregasi pemukiman berdasarkan agama menjadi semakin ketat.
Diferensiasi pola relasi agama dan sosio-kultur di ketiga wilayah ini akan memudahkan kita memahami pola konflik dan mekanisme penyelesaiannya yang berbeda di ketiga wilayah tersebut, dan pendekatan kultur menjadi penekanan utama dalam penyelesaian konflik di ketiga wilayah tersebut. Perbedaan tarikan dan kepentingan politik di Wilayah Maluku Tengah, khususnya Ambon sebagai pusat politik dan sumbu awal konflik menjadikan pendekatan politik lebih dominan dibandingkan pendekatan kultur dalam proses rekonsiliasi di wilayah ini dibandinngkan 2 wilayah lainnya.
Karakterstik militansi keberagamaan orang Maluku cukup kuat, sehingga stigma teologis akan lebih memancing emosi dibandingkan stigma moral. Misalnya orang Maluku akan lebih tersulut emosinya jika disebut kafir dibandingkan disebut bajingan. Komitmen militansi keagamaan ini tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan ketaatan normatif beragama. Orang yang jarang salat atau jarang ke gereja sekalipun, emosinya akan mudah tersulut jika diprovokasi dengan atas nama agama. Hal ini kerap berkelindan dengan militansi emosional dengan ikatan suku, negeri, atau kampong/ohoi-rat-schaap. Terkhusus di Utara dan Tengah identitas agama biasanya identik dengan suku dan negeri, misal di Utara, Suku Makian yang Muslim dan Suku Kao yang Kristen atau contoh Negeri Batumerah yang Muslim dan Negeri Passo yang Kristen. Di Maluku Tengah konflik antar dua negeri yang seagama juga biasa terjadi dan berlangsung secara turun-temurun, misalnya antara Negeri Mamala dan Morella, Negeri Seit dan Negeri Lima yang seagama. Sedangkan untuk di Wilayah Tenggara, khsuusnya di Kepulauan Kei. Di Utara perseteruan dalam hal perebutan pengaruh antara Ternate dan Tidore juga menjadi satu variabel untuk membaca ekses-ekses konflik yang terjadi.
Pasang-surut hubungan antara Salam-Sarane di Maluku telah teruji selama ratusan tahun, harmoni basudara Salam-basudara Sarane hingga konflik Acank-Obet mewarnai fase berabad hubungan antara keduanya. Harmoni budaya mendamaikan dan tarikan ekonomi politik mencerai-beraikan. Sejak masuknya agama (Islam dan Kristen) di Maluku, diferensiasi penduduk berdasarkan agama pun terjadi. Diferensiasi ini berpengaruh pada kompetisi kultur, ekonomi, dan politik yang mengakibatkan hubungan antar keduanya berlangsung pasang-surut. Pasang dan surut relasi ditandai dengan konflik dan harmoni yang datang silih berganti dan lebih dipengaruhi oleh tarikan kepentingan ekonomi dan politik. Variabel ekonomi dan politik harus digarisbawahi sebagai pemantik utama konflik dan faktor agama sebagai sumbunya. Ekses dan eskalasi konflik semakin kuat dan meluas jika tarikan kepentingan ekonomi politiknya juga kuat dan luas, apalagi jika tarikan tersebut melibatkan kepentingan elit nasional dan bahkan konspirasi global.
Sejak zaman kolonial, Ambon ditetapkan sebagai pusat wilayah Maluku, sentralisme Ambon atas Maluku berlangsung hingga masa-masa kemudian. Ambon menjadi penanda nama yang menggantikan nama Maluku ketika anak-anak Maluku menyebutkan asal daerah mereka, meski mereka berasal dari daerah Kei atau Ternate yang sangat jauh dari Ambon. Sentralisme Ambon (kota) membuat riak ekonomi dan politik yang terjadi di Ambon dengan sangat mudah dan cepat menyebar ke wilayah Maluku lainnya. Hal ini kemudian menjadi alasan kenapa konflik atas nama agama di Ambon dengan cepat menyebar melintasi lautan hingga ke Utara dan Tenggara, dengan tentu saja tidak menafikan faktor-faktor lokal yang menjadi pemantik lokalnya. Misalnya perseteruan dominasi Ternate-Tidore di Utara yang kemudian mentransformasi konflik, dari konflik antara Suku Kao Kristen dan Makian Muslim menjadi konflik antara Pasukan Kuning dan pasukan Putih atau konflik antara Tual (Muslim) dan Ta’ar (Kristen) di Tenggara.
Di masa rezim Orde Baru keadaan berbalik, umat Muslim Maluku, khususnya dari Haruku menguasai birokrasi pemerintahan dan etnis Muslim pendatang dari Buton-Bugis-Makassar (BBM) menguasai sektor ekonomi. Kalangan Kristen hanya “berkuasa” pada wilayah akademik di Universitas Pattimura.
Gap inilah yang kemudian dikelola menjadi sentimen sosial sebagai pemicu konflik plus kepentingan elit nasional dan politik internasional yang bermain menjadikan Maluku sebagai medan Kurusetra tempat pertempuran kolosal antara dua kelompok yang bersaudara. Hanya butuh waktu yang sangat singkat untuk memutasi isu antara pribumi-pendatang (BBM) menjadi isu agama (Islam-Kristen), karena relasi agama antara keduanya bagai bara yang telah lama bersemayam di tanah Maluku akibat politik diferensiasi yang dilakukan oleh rezim kolonial dan orba. Darah dan air mata tertumpah, tak terhitung korban terluka dan meregang nyawa, kehilangan tempat tinggal dan sanak saudara, kehilangan senyum dan tawa berganti tumpahan darah dan derai air mata. Konflik Maluku meninggalkan luka yang sangat dalam dan membutuhkan recovery yang sangat panjang dan lama.
Hubungan antara Muslim dan Kristen diwarnai konflik dan harmoni, konflik merambah hingga persitegangan klaim apakah kata Maluku berasal dari bahasa Arab atau Ibrani, pahlawan Pattimura bernama asli Ahmad atau Thomas hingga persitegangan fisik yang dipicu oleh tarikan kepentingan ekonomi dan politik. Hubungan harmonis juga kerap mewarnai relasi antara basudara Salam dan basudara Sarane.
Ikatan darah dan adat menjadi pengikat kohesi sosial dan media rekonsilliasi ketika terjadi konfik. Gandong dan Pela (Tengah), Larvul Ngabal dan Ain ni Ain (Tenggara), serta persaudaraan Maloko Kie Raha menjadi pengikat kohesi sosial dan ketika konflik dimanfaatkan sebagai pranata rekonsiliasi. Wilayah Tenggara menjadi daerah yang paling cepat rekonsiliasi karena adanya netralitas Katolik sebagai pihak ketiga dan wilayah Tenggara khususnya sebagai “benteng terkuat” terakhir dari adat Maluku dan ini berhasil dikelola secara efektif oleh tokoh agama dan tokoh adat setempat. Wilayah Tengah menjadi wilayah yang paling lama rekonsiliasi dan kerugian jiwa dan harta yang paling besar, karena posisi sebagai sentral dan kuatnya tarikan ekonomi serta politik, sehingga mekanisme rekonsiliasi harus dengan pendekatan intervensi pusat melalui konferensi Malino tahun 2002.
Setelah lebih satu dasawarsa berlalu, ternyata konflik dan kekerasan Maluku masih menunjukkan sifat latennya sehingga kondisi damai yang terjadi ini masih sangat rentan dan sangat memungkinkan untuk konflik terjadi kembali. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan upaya fundamental untuk membangun kembali tatanan sosial masyarakatnya yang telah hancur ini dengan harapan agar konflik dan kekerasan yang pernah terjadi tidak terulang di masa mendatang dengan menengok kembali seraya mengevaluasi apakah upaya-upaya penyelesaian konflik yang pernah dan sedang dilakukan telah sesuai dengan apa yang niscaya dilakukan.
Sebab, disadari maupun tidak, konflik Maluku yang terjadi berkepanjangan ini telah menyeret dan melibatkan semua unsur didalamnya, termasuk agama. Selain faktor segregasi sosial kewilayahan berdasar agama, terseretnya agama selama konflik Maluku 1999 menjadikan integrasi sosial masyarakatnya semakin sulit terwujud sebagaimana sediakala sebagaimana sebelum konflik terjadi.
Untuk terulang terjadinya konflik kolosal sebagaimana dahulu tentu saja hal yang hampir mustahil. Maluku telah 2 kali lolos dari “lubang jarum” konflik ketika pemilihan gubernur 2013 dan 2018. Sesaat setelah kedua momen tersebut berlangsung dan merasakan secara langsung tidak adanya efek pergesekan agama karena momen tersebut, meski tak bisa dipungkiri secara “terselubung” preferensi agama tetap masih dimainkan oleh sebagian pihak, namun tidak bertransformasi menjadi konflik horisontal agama. Kekisruhan politik yang terjadi benar-benar lebih pada kekisruhan politik yang “murni” atau “steril” dari pengaruh agama. []