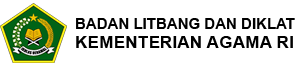Privilege (Gelar) Haji di Gorontalo

Oleh:
Muh. Irfan Syuhudi (Peneliti Balai Litbang Agama Makassar)
MALAM itu, Ibu Muna, yang berencana berangkat haji, tampak berbahagia. Para tamu satu per satu menyalami dirinya. Dengan mengundang beberapa tetangga di kediamannya, di Kota Gorontalo, perempuan berusia 52, itu baru saja melakukan ritual yang dinamakan “Baca Doa”, yaitu sebuah ritual berkaitan keberangkatan haji. Ritual “Baca Doa” berisi tadarrusan (mengaji), zikir, dan Salawati (Salawat Nabi Muhammad SAW).
Ibu Muna dan sebagian besar masyarakat Gorontalo meyakini, “Baca Doa” dimaksudkan untuk kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan kesehatan calon jemaah haji sejak meninggalkan rumah, hingga balik lagi ke rumah. Juga, dimaksudkan supaya calon jemaah haji dapat melaksanakan semua Rukun Haji tanpa menemui kendalam dan memperoleh Haji Mabrur.
Gorontalo sejak dulu terkenal sebagai daerah yang kental dengan tradisi dan ritual. Semua aktivitas kehidupan manusia hingga kematian (life cycle), dipastikan diadakan “upacara” ritual. Selain ritual “Baca Doa”, calon haji juga diminta menyiapkan diri lahir batin, seperti membersihkan pikiran dan perilaku.
Selain “Baca Doa”, calon jemaah haji kerap juga melakukan kebiasaan tertentu sebelum berangkat haji, yaitu “pembersihan diri”, sehingga ada ungkapan: “Berhaji di sini dulu (Gorontalo). Masa’ mau kotor-kotor pergi ke sana (Tanah Suci).” Menurut Qadhi Wilayah Provinsi Gorontalo, KH. Abdurrasyid Kamaru, yang saya temui di Gorontalo, ungkapan tersebut dimaknai sebagai refleksi diri. Maksudnya, orang yang merencanakan pergi haji sebaiknya banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Mereka akan menuju ke tempat yang disucikan Allah.
Katakanlah, kata KH. Abdurrasyid Kamaru, mereka yang dulunya malas bersedekah, kebiasaan itu harus diubah menjadi rajin bersedekah. Mereka yang tadinya jarang ke masjid, menjadi mulai rajin berjemaah di masjid. Mereka yang dulunya selalu merasa hebat atau angkuh, mulai menghilangkan sifat merasa diri paling hebat dari orang lain.
Bagi orang Gorontalo, naik haji adalah peristiwa yang sangat disakralkan, dan diibaratkan menuju kematian. Tak ada yang bisa memberi garansi, mereka akan balik lagi bertemu keluarganya. Boleh jadi, setibanya di Makkah, mereka akan menderita sakit, atau bahkan meninggal. Karena itu, sebelum berangkat haji, calon haji telah menyiapkan segala sesuatunya untuk keluarga yang mereka tinggalkan di rumah.
Dalam istilah Asrul Lasapa, Kasi Pembinaan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Gorontalo, orang yang akan berangkat haji disamakan pergi membawa keranda mayat, yang diartikan “(anggaplah) calon jemaah haji itu sudah meninggal”. Tak mengherankan, begitu pulang ke tanah air, dan tiba di rumah, mereka disambut dengan perasaan suka cita oleh seluruh keluarga dan kerabat.
Yang menarik dari gelar haji adalah, adanya penyematan identitas baru, berupa “kenaikan” status sosial dan spiritual dari masyarakat sekitar. Hampir semua tulisan menyebutkan, orang yang telah bergelar haji akan mendapatkan privilege (keistimewaan), seperti sebutan alim dan orang kaya dari lingkungan tempat tinggalnya. Hal tersebut dapat dimaklumi, lantaran untuk bisa berhaji, seseorang perlu mempersiapkan pengetahuan keagamaan dan ekonomi (uang).
Maka dari itu, dalam kasus tertentu, ada juga orang yang berangkat haji, karena lantaran ingin dipanggil “haji dan hajjah”, dan tersinggung bila ada yang memanggil namanya tanpa menyertai embel-embel “haji dan hajjah”. Pada orang semacam itu, mereka berhaji untuk menambah modal sosial (Zainul Maarif, 2017).
Anik Farida, yang meneliti pedagang Betawi menyebutkan, gelar haji bisa membuat yang bersangkutan “naik kelas”. Malah, gelar haji disejajarkan dengan elite keagamaan, seperti halnya kyai atau ulama, tanpa memandang kualitas keagamaan bersangkutan (Farida, 1999). Ini juga menunjukkan, gelar haji dapat membuat seseorang dilabeli alim dan dianggap memahami agama tanpa melihat latar belakang tingkat pendidikan dan kualitas keagamaan mereka.
Demikian pula, pada masyarakat pedesaan Madura. Naik haji ikut berdampak terhadap kehidupan sosial mereka dan keluarga. Setidaknya, seseorang yang bergelar haji akan mendapatkan perlakuan istimewa dari lingkungan sosialnya, khususnya pada upacara-upacara keagamaan dan siklus hidup (life cycle). Setiap kali mendapat undangan menghadiri upacara sosial dan upacara keagamaan, para haji diberikan tempat duduk terhormat, sejajar dengan para tokoh agama (Madani, 1984).
Betapa pentingnya pencapaian gelar haji, sehingga sebagian besar masyarakat di sana menganggap, berangkat haji sebagai bagian dari cita-cita hidup yang harus mereka penuhi, tanpa memedulikan lagi apakah proses berangkat haji ini nantinya bakal menguras harta mereka atau mempengaruhi kehidupan ekonomi mereka kelak (Madani, 1984).
Identitas Baru
Dalam memandang gelar haji, orang Gorontalo tidak menilai dari tingkat pendidikan yang bersangkutan. Artinya, sepanjang orang itu bergelar haji, masyarakat spontanitas memberikan kesan positif kepada mereka. Beberapa identitas sosial baru pun secara otomatis melekat pada diri seorang haji. Selain disegani, dihormati, dan diberikan kedudukan penting pada upacara-upacara sosial, juga mereka dianggap lebih memahami agama Islam. Karena itu, ketokohan seseorang di tengah masyarakat terkesan belum lengkap apabila belum bergelar haji.
Dalam konteks Gorontalo, kedudukan tokoh agama dianggap lebih spesial dibanding posisi lain. Sebab, dalam diri seseorang terkadang melekat beberapa status, misalkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pejabat. Orang yang bekerja di instansi kementerian agama, misalnya, terkadang dilabeli oleh masyarakat dengan tiga status sosial tersebut (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pejabat).
Orang Gorontalo berpandangan, haji adalah gelar tertinggi umat Islam. Ia berbeda, dan tidak bisa disamakan dengan gelar formalistik yang diperoleh di bangku sekolah. Haji adalah panggilan Allah, dan orang-orang yang memenuhi panggilan Allah sajalah yang akan berkunjung melaksanakan Rukun Islam kelima itu. Gelar haji selalu dikaitkan dengan tindakan dan perilaku. Apabila setelah berhaji dan perilakunya berubah, terutama terlihat lebih agamis, masyarakat beranggapan orang itu betul-betul layak menyandang gelar haji.
Sebaliknya, apabila perilaku seorang haji itu didalam kehidupan sehari-hari terlihat tidak mengalami banyak perubahan, dan justru tetap melakukan perbuatan yang dilarang agama, masyarakat menganggap orang tersebut belum berhak bergelar haji.
Alhasil, tanpa disadari oleh seorang haji, masyarakat sebenarnya yang terkadang memberi penilaian terhadap gelar haji seseorang, dengan membandingkan perilaku orang bersangkutan sebelum dan pasca berhaji. Dengan kondisi seperti itu, masyarakat pula yang kemudian mendefinisikan apakah orang itu benar-benar telah berhaji atau tidak, dengan mengamati perilakunya (akhlaknya).
Dari sini dapat dilihat, segala perilaku orang yang bergelar haji akan terus diawasi oleh masyarakat. Mereka akan menjadi tatapan sosial, baik di ruang domestik maupun publik. Ibarat menara pengawas (panopticon), istilah Foucauldian, gelar haji menjadi pengontrol atas apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Gelar haji juga akan mendisiplinkan tubuh, baik dalam perilaku, tindakan, maupun cara berpakaian di ruang publik. Dengan gelar haji, mereka akan merasa diawasi oleh masyarakat, sehingga khawatir melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan stigma negatif kepada yang bersangkutan.[]
Sumber foto: google
M. Irfan Syuhudi/diad