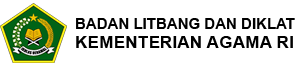Tanduale: Sumpah Setia Persaudaraan antar Etnis

Muh. Subair
Saya tidak ingat, kapan terakhir kali sebuah cerita menggidikkan bulu kuduk, rasanya sudah lama sekali, mungkin di masa masih kecil dengan kepekaan rasa yang masih cukup tajam. Katanya kepekaan seseorang bisa menjadi luntur seiring semakin bertambahnya usia, atau mungkin kepekaan itu terkikis oleh tumpukan pengalaman hidup yang datang silih berganti. Sehingga unsur-unsur kejutan menjadi lumrah dan membuat orang menjadi terbawa santai dalam menghadapi fluktuasi situasi dan kondisi. Tetapi tidak ketika mendengarkan cerita tentang Tanduale.
Berawal dari kisah seorang perantau Bugis dari suatu kerajaan kecil yang mengarungi lautan untuk mencari kehidupan yang lebih damai, yaitu demi menyelematkan putra mahkotanya dari ancaman amukan perang Makassar (1669 M). Mereka berangkat dari Pulau Sembilan menuju ke tempat-tempat yang senantiasa dikunjungi oleh nenek moyangnya. Selanjutnya mereka menetap di tanah Buton yang terkenal memiliki hamparan alam yang menjanjikan.
Sebuah kabar yang akrab akibat kekerabatan Bugis dan Buton memang telah lama terjalin, sebagaimana disebutkan dalam tradisi lisan masyarakat, bahwa Sawerigading pernah menjalin perkawinan dengan putri raja Buton bernama We Tenri Dio, yang kemudian keturunannya dipercaya menjadi raja-raja berbagai kerajaan kecil di Buton.
Ketika itu, kedigdayaan pelaut Bugis telah dikenal malang melintang di berbagai wilayah di Asia. Perantau Bugis ternyata adalah seorang raja sekaligus murid dari Datuk Ditiro yang menyamarkan diri dengan menggunakan nama La Bolong (Subair, 2014: 177). Tiba di Tinanggea yang masuk dalam wilayah kekuasaan kesultanan Buton, perantau Bugis menyusuri daerah bebatuan sampai menemukan rumbia yang berdiri berjejer dengan dedaunan melambai seolah memberi ucapan selamat datang.
Rumbia itu menuntun mereka menyusuri sebuah muara sungai yang memberikan kuatnya tanda-tanda kehidupan di permukaannya. Pelaut-pelaut Bugis sudah bisa mafhum tentang hidup matinya suatu daerah yang dilaluinya dengan hanya mengamati situasi alam, apakah sungai tersebut sering dilalui oleh manusia atau hanya makhluk-makhluk buas yang ada di dalamnya.
Sang raja memerintahkan sandeq-sandeq untuk merapat, dan segera mengambil inisiatif untuk menemui raja atau penguasa setempat, dari kejauhan terlihat ada beberapa bangunan di kaki bukit, rumah-rumah itu tentu tak jauh dari sumber air, atau bisa dipastikan mereka berada dekat dari hulu sungai.
La Bolong meminta beberapa pengikut mendampinginya untuk menemui penguasa setempat, tidak dengan melalui hutan, tetapi dengan cara melawan arus sungai, mungkin untuk membuktikan kelihaian mereka di atas air, sekaligus menghindari bahaya yang mengancam jika menempuh jalur darat dengan melewati hutan-hutan.
Kisah yang dituturkan dalam bahasa Bugis ini malah terdengar aneh dan tidak masuk akal, alih-alih menggidikkan bulu kuduk. Namun, bukan pada saat cerita ini dituturkan bulu kuduk saya berdiri, melainkan setelah berkali-kali bermimpi mengarungi sungai dengan melawan arus, dan baginda raja La Bolong Daeng Makketti datang menemui saya seolah memperlihatkan cara mereka menaklukkan sungai dengan melawan arus, yaitu dengan mengayuh perahu secara zigzag, seolah hendak menyeberang dari tepian kiri ke tepian kanan dan sebaliknya dari tepian kanan ke tepian kiri, begitu seterusnya sampai mereka mencapai hulu sungai.
Penguasa setempat tidak sembarang menerima tamu, dan hanya mereka yang mempunyai keahlian tersendiri bisa mencapai tempat jauh dengan cara yang tidak biasa. Tentu yang datang ini juga merupakan seorang penguasa, maka ruang negosiasi dan komunikasi pun terbuka. Ringkasnya, sang raja La Bolong menawarkan kedamaian yang kemudian disepakati penguasa setempat yang belakangan dikenal sebagai raja Moronene. Saat itulah lahir yang namanya Tanduale, sebuah perjanjian untuk berdampingan hidup damai.
Tanduale, dalam bahasa Moronene berasal dari kataTundarie leemiu yang berarti pengikatan kekeluargaan, dan dalam bahasa Bugis berasal dari kata Tanro ale,tanro berati sumpah, ale berarti diri, yaitu sumpah terhadap diri sendiri. Masing-masing kedua belah pihak bersumpah dan berjanji kepada diri sendiri.
La Bolong (Tamana Raiyyah, disebut Daeng Makketti Raja Maningpahoi dari Sinjai) bersama dengan Tamana Kelu (Raja Moronene, nenek dari Raja Pimpi), melakukan sumpah perjanjian di atas tanah Mattanro Ale, yang terletak di gunung Mandoke di sekitar lingkar Bukori.
Wilayah ini merupakan pertemuan antara beberapa suku di Buton, yang membuka kemungkinan kegiatan tersebut tidak hanya dihadari oleh kedua suku tersebut saja. Sumpah dilakukan dengan upacara adat dan diberlakukan untuk tujuh turunan yang ditandai dengan meminum air dari cawan yang sama. Dari atas bukit itu mereka menyepakati wilayah pesisir sebagai daerah bebas untuk orang Bugis mendirikan rumah-rumah dan melakukan pengolahan lahan. Sedangkan daerah hamparan kaki bukit, adalah wilayah orang Moronene yang sudah didiami sejak lama dengan rumah-rumah, sawah-sawah, dan kebun-kebun yang telah mereka garap. Wilayah ini tidak boleh diganggu oleh orang Bugis.
Inti sumpah Tanduale adalah perjanjian persaudaraan antara Bugis dan Moronene, bahwa mereka tidak boleh saling menyakiti atau saling merugikan. Siapapun melanggar akan berakibat berumur pendek. Jika terdapat orang Moronene yang mengalami kesusahan di lautan, maka orang Bugis berkewajiban memberikan bantuan. Sebaliknya, jika orang Bugis mengalami kesusahan di daratan, maka orang Moronene berkewajiban membantunya.
Suatu ketika pernah ada yang melanggar sumpah tersebut. Seminggu setelah kejadiannya, orang yang melanggar sumpah itu benar-benar meninggal. Pasca tragedi itu, persaudaraan antara Moronene dan Bugis kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tak ada yang berani menyakiti satu dengan yang lain.
Saat peristiwa DI/TII, pasukan Kahar Muzakkar ketika itu mengambil alih wilayah pemukiman Moronene. Orang-orang Moronene yang rumahnya diambil memilih bergabung bersama masyarakat Bugis di bawah perlindungan TNI. Karena perang yang berlangsung lama, maka mereka membagi diri ke dalam rumah-rumah orang Bugis, satu rumah keluarga Bugis paling tidak menampung dua atau tiga keluarga Moronene. Momen itu memperteguh persaudaraan mereka menjadi lebih intim hingga kini.
Persaudaraan yang terjalin tidak memandang agama, di mana sebagian dari orang Moronene dari keturunan rumpun keluarga Raja Powatu mayoritas beragama Kristen, jika ada yang Islam maka dipastikan ia muallaf, demikian dari keturunan Raja Monara adalah mayoritas beragama Islam. Namun dalam kehidupan sehari-hari, mereka tetap saling bersaudara. Orang Bugis memanggil saudara Moronenenya dengan sebutan Tokia, dan orang Moronene memanggil saudara Bugisnya dengan sebutanSlessureng.
Kisah di atas dialami pula oleh Idrus, lelaki asal Bugis. Ia mengenang ketika orang tuanya masih hidup. Idrus sering disuruh untuk mengantar makanan kepada saudaranya yang Moronene, baik yang Islam maupun Kristen. Akhirnya menjadi kebiasaan, merasa tidak enak menikmati suatu makanan jika tidak dibagi kepada keluarga, begitu juga sebaliknya.
Sejalan dengan Arsyad yang menuturkan bahwa ketika memperoleh hasil laut, ia selalu mengantarkannya ke rumah saudara Moronene. Di sana orang Bugis selalu dijamu makan. Biasanya orang Moronene juga memberi hasil bumi sebagai imbalan terima kasih.
Sayangnya, persaudaraan ini mulai merenggang sejak terjadinya pemekaran wilayah yang menjadikan Bombana sebagai kabupaten tersendiri. Selain itu, menguatnya politik identitas menggilas persaudaraan yang telah dibangun sejak lama oleh nenek moyang kita. Sehingga perlu dibangkitkan kembali kesadaran masyarakat akan sumpah janji Tanduale.
Pudarnya persaudaraan antar etnis harus menjadi daya dorong untuk menghidupkan kembali tradisi yang mengikat perdamaian. Lagi pula, Tanduale bukan sekedar antara Moronene dan Bugis yang ada di Rumbia Bombana. Tanduale juga dikenal oleh masyarakat Bugis dan Moronene di daerah Poleang, khususnya dari keluarga Intama Ali.
Saenal (2018, p. 1) menyebut peristiwa Tanduale terjadi pada abad XVIII yang terjadi di wilayah Poleang. Hal ini juga diungkap oleh seorang peneliti dari IAIN Kendari (Abbas Tekeng 45, Kendari, 26 Maret 2019). Bahkan tradisi ini mulai kembali diperingati di wilayah Poleang sebagai bentuk pembaharuan janji atau sumpah, sebagai refleksi atas sebuah peristiwa pelanggaran terhadap Sumpah Tanduale. Pada tanggal 9 Februari 2019 yang lalu, berdasarkan info dari www.harapansultra.com, telah dihidupkan kembali acara adat Tanduale. Acara ini dihadiri oleh perwakilan adat dari dua kabupaten (Kolaka dan Bombana), yakni Mokole Rumbia, Apua Mokole Kotua, Masyarakat Adat Jawa, Bali, Bugis, Mekongga, dan Bupati Kolaka yang diwakili asisten I Pemda Kolaka. Masyarakat berharap ikatan persaudaraan ini dapat berlangsung seumur hidup, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa akan termakan sumpah apabila ada yang melanggarnya. []
Muh. Subair/diad
Sumber foto: google.com