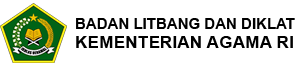Ulama, Kepemimpinan Lokal, dan Good Governance di Sulawesi Selatan

Abd. Kadir Ahmad (Peneliti Utama Balai Litbang Agama Makassar)
Ulama di Sulawesi Selatan
Ulama di Sulawesi Selatan, khususnya di kalangan Bugis-Makassar, adalah mereka yang oleh komunitas spiritual (spiritual community) diidentifikasi sebagai seorang ahli dalam bidang agama (Islam) yang diterima dan ditokohkan oleh komunitas spiritual tersebut sebagai Gurutta (Bugis) dan Gurunta (Makassar) (Boston, 1964). Pada saat ulama mencapai ke tingkat ahli, masyarakat Bugis menyebutnya topantira, atau tupanrita (Makassar).
Gurutta/gurunta adalah sebutan umum untuk ulama Bugis-Makassar. Di bawah gurutta terdapat para ustaz dan diatas peringkat gurutta terdapat anregurutta atau topanrita. Struktur ulama ini memperlihatkan fenomena paramida menurut kompetensi keilmuan, sosial, dan kepribadiaan yang dimilikinya. Para ustaz menempel dasar piramida dengan jumlahnya yang besar, sementara bagian tengah terdapat gurutta/gurunta dan di puncak paraminda terdapat level anregurutta/anrongurunta.
Konsep ulama bagi orang Bugis-Makassar hanya berlaku bagi ahli agama, dan tidak sepenuhnya sama dengan ulama menurut konsep Alquran, dimana konsep ulama mencakup bukan hanya ahli dalam bidang ilmu keislaman dalam arti sempit, tetapi juga ahli ilmu kealaman dan sosial. Ahli agama tersebut secara khas memiliki kemampuan dalam penguasaan kitab klasik yang disimbolkan melalui apa yang disebut orang Bugis-Makassar sebagai kittaq gondoloq (kitab yang tulisannya tidak menggunakan syakal) yang diperolehnya melalui lembaga pendidikan pesantren atau madrasah. Setara dengan keahlian khas tersebut, ia merefleksikan ilmunya ke dalam bentuk konkret integritas kepribadian menurut ukuran komunitas spiritual yang dibangunnya.
Ulama bagi orang Bugis-Makassar, bukanlah suatu gelar akademik, melainkan gelar yang diberikan oleh masyarakat untuk seseorang yang dianggapnya memenuhi kualifikasi tertentu. Meski bukan gelar akademik, keahlian dalam bidang agama tetap menjadi dasar penilaian. Hal ini sesuai dengan pengertian dasar gurutta/guruntaitu sendiri sebagai orang yang dapat menjadi tempat bertanya atau rujukan tentang hukum syariat karena kedalaman dan keluasaan ilmunya.
Penguasaan kitta gondoloq, yang di Jawa disebut dengan kitab kuning, dipandang penting karena seorang ulama tidak boleh tergelincir dalam kesalahan yang dianggap prinsip, seperti keliru dalam pengucapan ayat atau hadis. Tradisi kittak gondoloq sampai sekarang masih berpusat di pesantren. Karena itu, orang Bugis-Makassar memandang ulama tidak dapat dilepaskan dari dunia pesantren.
Posisi sebagai rujukan inilah yang membedakan tingkatan keilmuan seseorang ulama sekaligus menunjukkan ruang wilayah pengakuan komunitas spiritual yang mengitarinya. Semakin tinggi tingkatan keilmuannya semakin luas pula jaringan dan wilayah komunitas spiritual yang dibangun dan merujuknya. Anregurutta, dengan demikian, bukan hanya dikenal dan dirujuk oleh masyarakat di wilayah tempat tinggalnya melainkan juga di luar batas-batas geografis dan sosiologis dalam skala yang luas.
Selain kompetensi keilmuan ulama di Sulawesi Selatan juga dilihat dari aspek praksis dalam bentuk pengalaman ilmu yang diketahuinya. Pengakuan komunitas spiritual tergantung pada penilaian terhadap amalan ulama. Ia akan diakui sebagai ulama setelah mampu meyakinkan masyarakat lewat pengalaman ilmu yang diketahuinya. Kenyataan menunjukkan, banyak orang yang ilmunya banyak akan tetapi sulit “melekat” pada dirinya titel ulama. Sebaliknya ada orang yang tidak memiliki titel akademik akan tetapi masyrakat mengakuinya sebagai ulama.
Aspek gauq atau amal meliputi amalan dunia dan akhirat. Begitu penting aspek pengamalan ini sehingga ulama mengatakan “kalau kamu menghafal satu hadis lalu mengamalkannya fatakun ȃliman (jadilah kamu ulama)”. Amal ini pula yang membedakan seseorang ulama dengan seorang ahli (pada bidang pengetahuan) agama. Amal diyakini sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh ilmu langsung dari Allah (ilmu ladunni). Hal ini terkait dengan keyakinan bahwa ilmu dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu melalui proses belajar mengajar dan ilmu yang (merupakan pemberian) langsung dari Allah.
Ilmu tersebut hanya dapat diperoleh apabila ilmu yang dimiliki diamalkan. Hai ini sesuai dengan riwayat: man ‘amila mȃ ya’lamu ‘allamahu al-lȃhu ‘ilman mȃlam ya’lam, (barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarinya pengetahuan yang ia belum ketahui). Demikian penting aspek praksis ini sehingga ulama mengidentikkannya dengan takwa. Takwa diartikan melindungi diri dari amalan yang menyimpang. Isu penting disini adalah konsep aga napau aga napigauq (Bugis) konsistensi kata dan perbuatan. Sebaliknya perilaku ulama yang menyimpang disindir dengan kiasan “sisalai bulunna tingkokona” (Makassar).
Kompetensi ulama yang lain adalah akhlak atau keperibadian. Dalam konteks budaya Bugis- Makassar, akhlak adalah sitinaja,yang lebih bersifat kepantasan daripada normatif. Hal yang paling muda disorot adalah performance kaitannya dengan etika dalam berpakaian, bertutur kata, dan bertingkah laku, serta kemampuan menjaga muru’ah, yang dalam konsep Bugis Makassar disebutmaniniq. Dari sinilah muncul panrita maniniq yang dapat disejajarkan dengan konsep ihtiyath, dalam tradisi ulama klasik.
Anregurutta atau topanrita, yang memiliki kualifikasi tertinggi dalam struktur ulama Bugis Makassar, dilihat dari pemilikan ketiga kompetensi di atas dapat disebut sebagai ulama kharismatik menurut Max Weber.
Ulama dan Kepemimpinan Lokal
Kemimpinan lokal di Sulawesi Selatan bersumber dari legitimasi sosio-kultural yang ditandai dengan penguasaan sesuatu yang bersifat sakral. Pemimpin komunitas dan seterusnya pemimpin kerajaan selalu bersumber dari mereka yang mampu mengaitkan dirinya dengan sifat sakral tersebut. Dari kedua sifat itulah kemudian muncul aspek darah atau keturunan (kebangsawanan). Jadi kebangsawanan di Sulawesi Selatan lebih karena adanya pemilikan sifat-sifat yang luhur daripada karena darah. Faktor darah hanya akibat dari sifat luhur.
Hal ini ditandai dengan proses terbentuknya masyarakat yang diawali dengan adanya gaukeng (Bugis) dan gaukang (Makassar) yang dipandang sesuatu yang sakral. Gaukeng adalah sesuatu benda dengan karakteristik yang khas baik berupa sebuah batu atau benda lainnya. Dipercayai bahwa pada suatu waktu anggota masyarakat tertentu menemukan benda suci. Orang yang menemukan benda suci itu kemudian diakui sebagai pemimpin komunitas dan sekaligus juru bicara gaukeng/gaukang. Sejak itulah komunitas dan kepemimpinan gaukeng/gaukang terbentuk (Andaya, 1981).
Menurut tradisi ini, komunitas-komunitas gaukeng menjadi semakin luas pada perkembangan berikutnya wilayah yang pada awalnya merupakan kawasan spiritual gaukeng/gaukang tidak mampu lagi menampung kebutuhan kelompok yang terus berkembang. Lahirlah komunitas-komunitas baru dengan gaukeng-nya masing-masing yang merupakan sub-sub dari komunitas induk. Kompleks-kompleks gaukeng kemudian terbentuk dan membuat pemimpin-pemimpin komunitas semakin banyak dan berkembang (Habot, 1996). Daerah tertentu masih mempertahankan komunitasgaukeng. Habot misalnya, melaporkan adanya komunitas gaukeng di Bontoramba salah satu desa di Gowa.
Komunitas gaukeng/gaukang yang semakin banyak tidak mampu lagi dipersatukan oleh pemimpin komunitas, sehingga akhirnya munculnya tokoh yang dipandang luhur dan sakral yang memilki kemampuan lebih tinggi yang disebut tomanurung (Bugis) atau tumanurung (Makassar). Konflik dan disintegrasi antara komunitas gaukeng tadi dipersatukan oleh tokoh tomanurung/tumanurung. Adanya kepemimpinan tomanurung merupakan cikal bakal berdirinya kerajaan –kerajaan di Sulawesi Selatan. Sama dengan pemimpin komunitas gaukeng/gaukang, seorang tomanurungdatang dengan benda-benda magis yang disebut arajang (Reid, 1987). Arajang, merupakan simbol legitimasi kepemimpinan komunits kecil (komunitas gaukeng),sedangkan arajang merupakan sumber legitimasi kerajaan sebagai perpaduan komunits-komunitas gaukeng/gaukang.
Dalam keadaan seperti itulah Islam datang dan berkembang di Sulawesi Selatan sejak abad ke-17 Masehi yang dipelopori oleh para ulama. Diterimanya Islam sebagai anutan oleh masyarakat membawa konsekuensi terbentuknya komunitas Islam di bawah kepemimpinan ulama.
Jika tomanurung merupakan tokoh pemersatu komunitasgaukeng/gaukang ke dalam suatu masyarakat kerajaan, maka kedatangan Islam yang dibawah kepemimpinan ulama mempersatukan kerajaan-kerajaan ke dalam suatu komunitas Islam yang lebih besar. Meski terjadi konflik antara beberapa kerajaan pasca penerimaan Islam, karena kehadiran kekuatan luar yang menganut politi pecah belah, namun peran ulama yang memimpin institusi syara (qadi, imam, katib, bilal dan doja) mampu meredam konflik yang lebih tajam.
Kepemimpinan ulama tidak saja terbatas pada lembaga formal yang disebut lembaga syara, melainkan juga lembaga-lembaga pendidikam, seperti pesantren dan madrasah, dan lembaga pengajian maupun majelis taklim, serta melalui pranata peribadatan. Ulama sebagai pemimpin umat memiliki jaringan, dengan kualifikasi ulama tersebut. Semakin tinggi kualifikasinya semakin luas pula jangkauan dan pengaruh kepemimpinannya.
Hubungan transmisi keilmuan antara anregurutta, gurutta, ustaz dan masyarakat membuat ulama memiliki network-nya sendiri. ada tiga network yang terpenting bagi ulama. Pertama, jaringan kekerabatan, kedua network pesantren atau madrasah dalam bentuk hubungan guru-murid dan hubungan murid dengan murid. Ketiga network organisasi (Abdullah, 1986).
Pola network semacam itu kadang kala sangat luas dan rumit yang hanya dapat ditelusuri melalui penelusuran yang cermat. Makna penting network secara konsepsional adalah munculnya apa yang disebut oleh Abdurahman Wahid, seperti dikutip Martin van Bruinessen, sebagai The Kiai behind the Kiais (kiai di belakang para kiai). Artinya di kalangan para guruttaa, ustaz dan para pemikir Islam, ada godfather-godfather-nya dan ada pula pengikut-pengikutinya (Bruinessen, 1986). Dalam konteks Sulawesi Selatan, topanrita atau tupanrita atau anregurutta adalah kiai behind the kiais tersebut.
Ulama dan Good Governance
Salah satu soal utama yang dihadapi pemerintahan daerah sekarang adalah menciptakan good govenrnance (pemerintahan yang baik) yang dipercayai sebagai salah satu prasyarat untuk mencapai kemaslahatan rakyat. Good Governance pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1991 dalam sebuah resolusi dari The Council of the European Community yang membahas Human Right, Democracy and Development. Di dalam resolusi itu disebutkan, salah satu prasyarat untuk mewujudkan sustainable development. Adalah dengan mewujudkan good governance. Dalam laporan lain disebutkan, good governance tidak bisa diwujudkan antara lain disebabkan adanya sistem kekuasaan yang tersentralisir, autokritik dengan birokrasi yang tidak efisian, disub-ordinasikannya institusi hukum, birokrasi dan lembaga pelayanan publik oleh kepentingan elite dan penguasa tertentu, sehingga mendorong munculnya praktik korupsi dan lemahnya akuntabilitas publik, kompetensi pengetahuan dan keterampilan para pejabat diberbagai jabatan publik dan politik amat rendah; serta tidak adanya partisipasi dan organisasi masyarakat sipil yang cukup kuat dalam proses pembangunan. Untuk itu diperlukan selain keterlibatan negara, juga sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan dalam setiap proses pembangunan (Widodo, 2001).
Kepemimpinan ulama dapat menjadi pintu masuk yang strategis bagi pemerintah untuk mewujudkan good governance. Penelitian menunjukkan bahwa peran ulama di dalam masyarakat bukan saja sebagai pemimpin lokal untuk komunitas tertentu, melainkan dalam skala yang lebih luas sebagai mediator dan motivator. Ulama amat berperan menghubungkan tradisi besar (ajaran Islam) dan tradisi kecil (praktek keagamaan di masyarakat) sebagaimana dikemukakan oleh Robert Redfield. Tradisi besar dan tradisi kecil juga digunakan G.E.von Grunebaum ketika menjelaskan gejala kesatuan dalam keragaman Islam di berbagai kawasan. Eric Wolf dan kemudian Geertz Javanese Kijaji” The Changing Role of A Cultural Broker mengembangkan teori tersebut menjadi ulama sebagai makelar budaya.
Meski menggunakan konsep yang berbeda pada intinya para antroplog tersebut melihat besarnya peran ulama sebagai mediator baik antara masyarakat lokal dengan sistem nasional bahkan internasional, juga mediator antara masyarakat dengan masyarakat. Bahkan secara khusus ulama menghubungkan umat dengan Tuhannya atau yang profan dengan yang sakral. Kapasitas seperti itu membuat ulama dipanuti dan dihormati, karena dipandang merupakan manifestasi-manifestasi dari realitas sakral (Durkheim, 2003).
Dari sudut pandang antropolog melihat pentingnya budaya dan tradisi dalam proses pembangunan. Mereka menekankan adanya “culture code”, yaitu cara-cara suatu budaya mengatasi setiap masalah yang terjadi. Cara penyelesaian masalah, dengan cara demikian akan berbeda antara satu budaya lainnya dan cenderung bertahan meski suatu budaya telah mengalami perubahan ke arah modernitas. Demikian juga untuk membangun good governancemaka potensi budaya dalam hal ini kepemimpinan lokal seyogianya dijadikan salah satu variable penting bahkan menentukan. Dengan cara tersebut paradigm modernitas (1) tidak selalu harus bersifat universal, tetapi terkait sepenuhnya dengan sejarah masyarakat bersangkutan, (2) harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan budaya dan sosial tertentu dan (3) memerlukan potret masyarakat dan budaya secara lebih kompleks daripada yang biasa dilakukan dengan paradigma lama. []
Abd. Kadir/diad